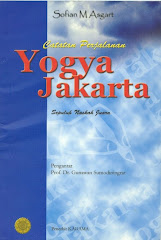Quo Vadis Gerakan Buruh ?
by. Sofian Munawar Asgart
Dalam konstelasi demokratisasi sejatinya buruh memiliki urgensinya tersendiri. Tidak berlebihan jika Rueschemeyer menyatakan bahwa kelas pekerja merupakan kekuatan pro-demokrasi utama. Setidaknya, ada tiga alasan penting mengapa buruh memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dibandingkan dengan kekuatan civil society yang lainnya. Pertama, buruh memiliki kemampuan “lebih” untuk memobilisasi massanya melakukan gerakan politik. Berbeda dengan kekuatan civil society lainnya, mobilisasi buruh kerapkali digerakkan atas dasar kesadaran kolektif –bahkan kesadaran kelas— setelah mengalami eksploitasi dalam hubungan produksi. Dalam banyak kasus di berbagai negara, buruh memiliki identitas politik yang lebih jelas dan militan yang berakar kuat pada sejarah yang dilaluinya. Kedua, gerakan buruh –berbeda dengan gerakan mahasiswa misalnya— dapat menimbulkan dampak ekonomi yang meluas baik bagi perusahaan maupun ekonomi makro suatu negara dalam bentuk berhentinya produksi. Ketiga, gerakan buruh dapat memicu munculnya persoalan sosial-politik baru terutama di daerah-daerah konsentrasi industri –bahkan dapat memaksakan pergantian rezim atau perubahan struktur politik.
Besarnya potensi gerakan buruh seringkali menjadi pemicu pemerintah untuk melakukan pengendalian yang serius. Upaya pengendalian ini antara lain dilakukan melalui represi, intimidasi dan politik pencitraan dengan membuat kesan negatif terhadap gerakan buruh agar gerakannya tidak meluas. Pada masa Orde Baru, misalnya, gerakan buruh selalu diasosiasikan dengan gerakan kiri-komunis yang anarkis. Upaya untuk membendung meluasnya gerakan buruh juga masih terus berlanjut hingga kini, bahkan masih dengan menggunakan cara-cara lama itu: represi, intimidasi, dan politik pencitraan. Wapres Jusuf Kalla, misalnya, menuding “aksi buruh ditunggangi pihak tertentu”. Sementara Presiden SBY mengeluarkan pernyataan tendensius yang lebih politis dan menyudutkan: “Aksi buruh yang anarkis itu telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak ikhlas atas hasil Pemilu 2004.”
Represi, intimidasi, dan politik pencitraan yang negative terhadap gerakan buruh ternyata tidak berhenti di aras struktural kekuasaan. Celakanya, hal itu justru telah berhasil direproduksi di aras societal. Ini terbukti, misalnya, menjelang perayaan Mayday 2006, hampir semua stasiun TV mengcover sejumlah kegusaran akan terjadinya kemacetan, anarkisme, dan situasi chaotic lainnya. Dengan begitu pencitraan ini pun kemudian tanpa disadari merasuk dan menyergap ruang kesadaran publik. Deretan persoalan ini tentu dapat diperpanjang lagi, termasuk dan terutama dari persoalan internal buruh itu sendiri. Yang pasti, sejumlah persoalan tersebut telah berpengaruh pada tersendatnya energi potensial gerakan buruh yang hingga kini belum mewujud menjadi energi kinetik yang produktif dan prospektif bagi terciptanya kondisi demokrasi yang bermakna.
Beberapa Kendala
Pakar perburuhan dari Universitas Stockholm, Bjorn Beckman, menilai bahwa kelas buruh di Indonesia telah gagal memberikan peran politiknya, termasuk dalam memberikan andil secara signifikan bagi tumbangnya rezim Soeharto. Menurutnya, kondisi ini disebabkan oleh fragmentasi di dalam gerakan buruh sendiri yang ditandai dengan munculnya pusat-pusat serikat buruh. Hingga kini tidak kurang dari 60 organisasi pusat serikat buruh. Fragmentasi ini tentu akan semakin tampak di level organisasi di bawahnya.
Sementara itu, aktivis FNPBI Dita Sari menilai bahwa pasca jatuhnya rezim Soeharto gerakan buruh sebenarnya juga menghadapi masalah yang lebih pelik. Menurutnya, pasar politik baru justru telah melahirkan otoritarianisme baru dimana terjadi kompetisi kaum borjuasi yang akan memposisikan buruh lebih sulit, bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat lokal karena kepentingan modal makin intensif dibackup oleh penguasa lokal.
Dalam kaitan itu, Olle Tornquist memberikan dua argumen penting mengapa buruh memiliki kontribusi lemah terhadap demokratisasi pasca Orde Baru. Pertama, bahwa kejatuhan Soeharto dan kelahiran demokrasi di Indonesia disebabkan oleh krisis, bukan oleh pembangunan atau modernisasi kapitalis yang didukung Barat. Bukan karena kapitalisme sedemikian dinamis dan progresif sehingga timbul kelas menengah liberal atau bahkan kelas pekerja yang kuat yang bisa mematahkan kungkungan represi. Sebaliknya, krisis secara massif mengurangi kekuatan tawar-menawar para buruh. Kedua, sejarah politik demokratisasi yang lemah. Menurutnya, ada sejumlah kendala yang dihadapi buruh, antara lain kuatnya fragmentasi gerakan buruh. Ini antara lain disokong empat basis utama, yaitu sentralisme, Ornop, sektor usaha dan pabrik, serta dana asing yang memecah belah. Di pihak lain, sebagian besar kalangan buruh juga menilai tidak ada kaitan antara perjuangan di tempat kerja dengan politik. Hal ini pula yang menyebabkan gerakan buruh menjadi sektoral.
Salah satu kesimpulan penelitian DEMOS mengenai “Masalah-masalah dan Pilihan-pilihan Demokratisasi di Indonesia“ juga menunjukkan bahwa agen-agen perubahan yang mengusung demokratisasi di Indonesia masih memposisikan dirinya sebatas sebagai aktivis masyarakat dan kelompok penekan, namun posisi dan peranan mereka mengambang di garis-tepi sistem demokrasi yang baru tumbuh, sehingga tidak mampu memberi dampak nyata bagi perubahan yang diharapkan. Selain itu, para aktivis pro-demokrasi juga tampaknya masih terfragmentasi. Aktivis buruh sebagai bagian inhern dari gerakan pro-demokrasi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari masalah ini. Beberapa data spesifik mengenai kondisi aktivis buruh juga dapat disimak dalam salah satu segmen hasil penelitian DEMOS yang akan menjadi pokok bahasan berikut.
1. Pesimisme menghadapi defisit demokrasi
Para aktivis pro-demokrasi yang menjadi informan riset DEMOS umumnya mempunyai pandangan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami defisit antara instrumen-instrumen kebebasan sipil dan politik –yang relatif lebih baik— dengan instrumen representasi dan pemerintahan yang menunjukkan kualitas sangat buruk. Sesungguhnya terdapat beberapa pola variasi di kalangan aktivis berbasis issu meskipun secara umum dapat dikategorikan pada dua kelompok besar, yakni yang memiliki sikap optimis dan pesimis terhadap instrumen representasi tersebut. Dalam hal ini, aktivis buruh boleh dibilang sebagai kelompok moderat dalam kaitannya dengan instrumen kebebasan sipil, namun sekaligus menjadi kelompok yang pesimis terhadap instrumen pemerintahan dan representasi. Potret ini dapat disimak dalam tabel berikut:
| No | Instrumen Kebebasan Sipil | Instrumen Pemerintahan dan Representasi |
| 1. | Politisi pro-demokrasi | 78 % | Aktivis Media | 23 % |
| 2. | Aktivis Rekonsiliasi | 72 % | Aktivis Gender | 21 % |
| 3. | Aktivis Buruh | 64 % | Aktivis HAM | 12 % |
| 4. | Aktivis HAM | 57 % | Aktivis Buruh | 11 % |
| 5. | Aktivis Gender | 55 % | Aktivis Miskin Kota | 1 % |
Sumber: Data DEMOS, diolah
2. Buruknya representasi di mata aktivis buruh
Sebagian besar informan riset DEMOS dari kalangan aktivis buruh menilai bahwa instrumen kepartaian dan pemerintahan sangat buruk kualitasnya. Tabel berikut merupakan penilaian atas beberapa instrumen representasi yang menurut informan dari aktivis buruh dipandang memiliki kualitas yang sangat buruk. Dalam hal kepartaian, misalnya, sebagian besar informan aktivis buruh (90%) menilai potret partai sangat buruk, baik dalam menganggregasikan kepentingan vital masyarakat, indepedensinya atas politik uang, maupun dalam hal tanggung jawabnya terhadap konstituen. Kemampuan partai membentuk dan menjalankan pemerintahan, bahkan kinerjanya lebih buruk lagi (95%). Potret yang sama buruknya juga terjadi dalam hal pemerintahan. Sebagian besar informan aktivis buruh (92%) menilai sangat buruk instrumen yang berhubungan dengan keterbukaan dan akuntabilitas birokrasi pada publik, kontak langsung masyarakat pada wakil politik dan dinas-dinas pelayanan umum, dan independensi pemerintah dari pihak asing. Instrumen paling buruk adalah independensi pemerintah dari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dimana 97% informan memberikan penilaian yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif aktivis buruh, persoalan representasi merupakan hal yang sangat krusial.
| No | Instrumen kepartaian yang buruk | Instrumen pemerintahan yang buruk |
| 1. | Partai yang mencerminkan issu dan kepentingan vital masyarakat | 90 % | Keterbukaan dan akuntabilitas birokrasi pada publik | 92 % |
| 2. | Independensi partai dari politik uang | 95 % | Kontak langsung masyarakat pada wakil politik dan dinas-dinas pelayanan umum | 92 % |
| 3. | Kontrol anggota terhadap partai dan tanggung jawab partai pada konstituen | 90 % | Independensi pemerintah dari pihak asing | 92 % |
| 4. | Kemampuan partai membentuk dan menjalankan pemerintahan | 95 % | Independensi pemerintah dari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi | 97 % |
Sumber: Data DEMOS, diolah
3. Karakteristik gerakan buruh
Hasil riset DEMOS menunjukkan bahwa dari beragam issu dan kepentingan yang diusung aktivis buruh, hanya sedikit agenda dan visi yang komprehensif. Sementara kapasitas para aktivis buruh dalam menghadapi problem-problem pemerintahan dan khususnya keterwakilan berkaitan erat dengan karakter issu-issu dan perspektif-perspektif kelompok-kelompok informan tersebut bekerja, masih tetap dominan.
 Ini menunjukkan kecenderungan umum, adanya dominasi kebijakan gerakan yang bertumpukan pada karakter issu dan kepentingan spesifik, yakni sebesar 46 persen. Sementara issu dan kepentingan umum sebesar 33 persen, sedang gagasan atau nilai-nilai umum hanya 31 persen.
Ini menunjukkan kecenderungan umum, adanya dominasi kebijakan gerakan yang bertumpukan pada karakter issu dan kepentingan spesifik, yakni sebesar 46 persen. Sementara issu dan kepentingan umum sebesar 33 persen, sedang gagasan atau nilai-nilai umum hanya 31 persen.
Dalam banyak kasus kita dapat melihat, misalnya demo-demo buruh yang massif umumnya dipicu oleh kepentingan “sempit” para buruh. Beberapa contoh misalnya demo kenaikan upah, revisi UU Ketenagakerjaan, atau bentuk-bentuk mogok kerja akibat hubungan industrial yang tidak harmonis. Sementara itu, dalam demonstrasi yang mengusung kepentingan demokrasi yang lebih “luas”, aktivis buruh tampaknya kurang proaktif.
Contoh nyata misalnya ketika para aktivis pro-demokrasi melakukan demontrasi menolak Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (UU APP). Pada momen itu, tampaknya kalangan buruh tidak cukup tersentuh. Padahal, secara langsung maupun tidak langsung hal ini juga memiliki keterkaitan dengan kepentingan para buruh juga.
Minimnya kesadaran “politis” di kalangan buruh tercermin pula dalam pilihan strategi, wilayah gerakan, dan metode mobilisasi yang ditempuh para aktivis buruh. Tabel berikut menunjukkan bahwa wilayah gerakan mereka cenderung bertumpu di “wilayah publik” dan wilayah “unit-unit swakelola”. Aktivis buruh cenderung menghindari aktivisnya pada hal-hal yang bersifat “politik-ekonomi” di wilayah Negara dan bisnis.
| No | Wilayah Gerakan Aktivis Buruh | F |
| 1. | Negara | 13 % |
| 2. | Bisnis | 9 % |
| 3. | Unit-unit swakelola | 30 % |
| 4. | Wilayah publik | 48 % |
Sumber: Data DEMOS
Meskipun banyak varian dan pilihan strategi yang ditempuh para aktivis buruh dalam mengejawantahkan perjuangannya, namun strategi yang ditempuh lebih banyak “melalui masyarakat sipil” (38%) ketimbang pilihan strategi lainnya. Ironisnya, strategi komprehensif justru menjadi pilihan yang unfavorable (5%). Namun begitu, dari segi metode mobilisasi, aktivis buruh telah menempuh cara-cara yang relatif berimbang dan cukup variatif. Hal ini dapat disimak dalam dua tabel berikut.
| No | Pilihan Strategi Aktivis Buruh | F |
| 1. | Melalui masyarakat sipil | 38 % |
| 2. | Melalui jalur judisial | 18 % |
| 3. | Melalui masyarakat sipil dan jalur judisial | 12 % |
| 4. | Melalui sistem legislatif | 8 % |
| 5. | Melalui sistem legislatif dan jalur judisial | 6 % |
| 6. | Melalui masyarakat sipil dan sistem legislatif | 14 % |
| 7. | Strategi komprehensif | 5 % |
Sumber: Data DEMOS
| No | Metode Mobilisasi Aktivis Buruh | F |
| 1. | Kepemimpinan popular | 16 % |
| 2. | Pola dukungan dan imbalan | 11 % |
| 3. | Pola kepemimpinan alternatif | 14 % |
| 4. | Jaringan | 28 % |
| 5. | Unit-unit yang terintegrasi | 31 % |
Sumber: Data DEMOS
Agenda ke Depan
Selain karakteristik gerakan aktivis buruh, hasil riset DEMOS juga memperlihatkan potret para aktor dominan di dunia perburuhan. Aktor dominan yang dimaksud di sini adalah aktor –baik secara personal maupun institusional– yang paling dominan dan berpengaruh di dalam konteks aktivitas perburuhan, baik pada tingkat lokal maupun nasional, di luar lingkungan gerakan pro-demokrasi. Dengan kata lain, aktor dominan di sini secara simplisistik dapat dipandang sebagai “musuh” para aktivis buruh. Setidaknya, ada lima kategori aktor dominan yang dianggap menghambat perjuangan aktivis buruh, namun yang paling utama adalah organ eksekutif baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal (40%) dan kalangan pengusaha (26%).
| No | Aktor Dominan menurut Aktivis Buruh | F |
| 1. | Organ eksekutif pusat/lokal | 40 % |
| 2. | Agen-agen represif | 5 % |
| 3. | Politisi oligarkis | 11 % |
| 4. | Pengusaha | 26 % |
| 5. | Pemimpin informal | 17 % |
| 6. | Lain-lain | 1 % |
Sumber: Data DEMOS
Dengan memahami faktor dan aktor penghambat, lalu apa yang seharusnya dilakukan para aktivis buruh ? Transisi demokrasi sungguh telah melahirkan kebutuhan yang sangat mendesak untuk merevitalisasi agenda demokratisasi. Olle Tornquist menyebutkan bahwa para aktor pro-demokrasi harus segera memutuskan apakah mereka akan meneruskan perjuangannya dengan cara yang lama atau beralih ke cara yang baru. Yang dimaksud dengan cara lama adalah perjuangan masyarakat sipil secara terbuka via a vis melawan negara seperti ketika berada di bawah rezim Soeharto. Cara yang baru adalah memberikan perhatian utama pada kepentingan yang sama, namun juga dalam kaitannya dengan negara dan politik, dan secara bersama-sama, selangkah demi selangkah, mencoba untuk mereformasi, mendemokratisasi, sekaligus menggunakan demokrasi.
Salah satu temuan penting Riset DEMOS menunjukkan bahwa begitu banyak issu dan kepentingan yang dibangun aktor pro-demokrasi, namun hanya sedikit agenda dan visi yang komprehensif. Hal ini juga terjadi di kalangan aktivis buruh dimana fragmentasi dan kepentingan sektoral masih menjadi mainstream. Karena itu sudah saatnya kaum buruh melakukan reorientasi gerakannya. Setidaknya, ada dua agenda mendesak yang penting dilakukan. Pertama, aktivis buruh harus segera mengubah pilihan strateginya dari sektoral menjadi gerakan simultan yang komprehensif. Agenda ini tentu saja secara langsung juga menuntut para aktivis buruh untuk bersikap lebih “politis” dengan menggeser gerakannya menuju “wilayah negara”. Kedua, melakukan broadening-base movement dengan membangun linkage bersama simpul gerakan pro-demokrasi yang lain sehingga tercipta new-democratic-pact di kalangan gerakan aktivis pro-demokrasi.***