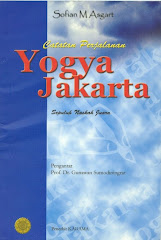Kamis, 16 Juli 2009
Minggu, 14 Juni 2009
HAM dan Pembangunan

Dari Pembangunanisme
ke Penghormatan HAM
Sofian Munawar Asgart ï
Pengantar
Dalam masa “jaya”-nya, jargon pembangunan seringkali menjadi “kata bertuah” tak terbantah yang mampu merubah banyak hal. Kesaktian ideom pembangunan memang diharapkan mampu menghadirkan solusi untuk setiap masalah, meskipun kenyataanya pembangunan seringkali juga menghadirkan sejumlah masalah untuk setiap solusi yang ditawarkannya.
Prestasi pembangunan yang kerapkali diagungkan ternyata bukan merupakan keberhasilan pembangunan itu sendiri. Idealisasi dan mistifikasi konsep dan paradigma pembangunan yang kemudian menjadi “pembangunanisme” itulah yang kemudian mengharuskan pembangunan “tidak boleh gagal”. Dengan menggunakan segala cara, ambisi untuk menyukseskan pembangunan kemudian berubah menjadi ideologi yang tak boleh dibantah. Karena itulah agenda pembangunan menjadi semu dan kadangkala harus berhadapan dengan persoalan kemanusiaan yang hakiki. Permasalahannya kemudian adalah bagaimana paradigma pembangunan diposisikan secara semestinya sehingga tidak berbenturan dengan penghormatan nilai-nilai kemanusiaan.
Risalah kecil ini memang tidak berpretensi untuk menganalisis secara kritis mengenai perspektif hak asasi manusia (HAM) dalam wacana pembangunan secara simultan. Uraian tulisan ini lebih merupakan elaborasi deskriptif mengenai pembangunan yang berwawasan HAM. Bagaimana latar historis konsepsi dan paradigma pembangunan ? Mengapa HAM harus dijadikan acuan dalam agenda pembangunan ? Bagaimana pula perspektif HAM diimplementasikan dalam konstelasi pembangunan di Indonesia ? Beberapa pertanyaan inilah yang akan dicoba untuk dijawab dan dideskripsikan dalam tulisan ini.
Kilas Balik Paradigma Pembangunan
Secara filosofis, kodrat manusia adalah essentia ut operatur, manusia adalah esensi yang ada dalam segenap aktivitasnya. Sementara itu, secara sosiologis, kodrat manusia selalu berada dalam suatu gerakan perubahan. Dalam hal ini, Thomas Hobes pernah mengemukakan suatu proposisi bahwa kehidupan yang bergerak itu bersifat abadi (vitamotus perpectus est), sedangkan Paschal dalam bahasa yang hampir sama mengatakan bahwa kodrat manusia itu berada dalam gerak dan perubahan, notre nature est dans le movement. Oleh karena itu, ‘pembangunan’ sebagai sebuah model perubahan memiliki relevansi sangat besar dengan kehidupan dan kodrat manusia itu sendiri.
Menurut Nisbet, pembangunan merupakan salah satu gagasan tertua dan terkuat dari semua gagasan Barat. Unsur utama perspektif ini menurutnya adalah metafora pertumbuhan, yaitu pertumbuhan yang terwujud dalam organisme. Sesuai dengan metafora ini, pembangunan dipahami sebagai suatu proses akumulatif terarah yang menghasilkan diferensiasi struktural dan peningkatan kompleksitas.[1] Sementara itu, Bjorn Hettne menilai bahwa pembangunan merupakan konsep terbuka sehingga harus didefinisikan secara kontekstual. Seiring dengan semakin mendalamnya pemahaman kita tentang proses, maupun sejalan dengan munculnya persoalan baru yang perlu dipecahkan, maka ‘pembangunan’ harus senantiasa didefinisikan kembali secara terus menerus.[2] Proses dialektis dari paradigma pembangunan ini yang dilukiskan oleh Paul Streeten bahwa “pembangunan menghadirkan solusi untuk setiap masalah, tetapi juga sekaligus menghadirkan masalah untuk setiap solusi”.[3]
Dalam lintasan sejarah, kita telah menyaksikan bahwa pasca Perang Dunia II Eropa yang hancur lebur begitu berambisi melakukan agenda pembangunan. Instrumen awal dalam pembangunan Eropa menurut Bjorn sejatinya adalah program bantuan besar-besaran dari Amerika Serikat melalui Marshall Aid. Program ini memiliki tujuan ganda, untuk menjalankan ekonomi dunia sesuai dengan sistem Bretton Woods dan sekaligus merupakan proyek untuk menahan lajunya komunisme sebagai bagian dari agenda Perang Dingin di antara mereka. Lebih jauh, Bjorn menilai bahwa rekonstruksi Eropa berhubungan langsung dengan persoalan pembangunan dalam bangsa-bangsa ‘baru’ yang dikenal dengan banyak istilah: terbelakang, belum maju, baru muncul, miskin, berkembang, dan lain-lain. “Ekonomi kolonial” menjadi “ekonomi pembangunan”. Karena itu, optimisme awal paradigma pembangunan ini harus dilihat pada latar sosio-historis keberhasilan pembangunan kembali Eropa.[4]
Selanjutnya, kolonialisme dan globalisasi telah menuntun negara-negara Dunia Ketiga mengadopsi resep pembangunan dalam beragam model dan bentuknya. Namun pada hakikatnya, paradigma awal konsepsi pembangunan banyak mencerminkan kepentingan elit penguasa di negara berkembang. Menurut Bjorn, paradigma modernisasi mengandaikan begitu saja bahwa masyarakat yang berciri kapitalisme industri diinginkan oleh semua, tetapi kenyataaannya tak seorang pun pernah memilih akumulasi modal dan industrialisasi, proses yang sering ditempuh adalah dengan menggunakan paksaan dan kekerasan. Semakin terbelakang suatu negara, tampaknya semakin banyak paksaan yang diperlukan. Elit yang menjalankan modernisasi, dengan cukup cerdik, bersikap diam terhadap perusakan kreatif yang mengerikan, atau apa yang disebut Peter Berger sebagai “piramida kurban”. Oleh karena itu, teori pembangunan tidak bebas nilai.[5]
Menurut Arndt, berkembangnya teori pembangunan dari model pertumbuhan yang sederhana ke arah teori perubahan sosial historis yang komprehensif dan holistik selain dapat dianalisis berdasarkan debat dimensi formalisme versus substantivisme, juga tercermin dalam pemilihan yang berulang-ulang antara pertumbuhan dan pembangunan.[6] Karena itu, meskipun perdebatan mengenai paradigma pembangunan terus berlangsung hingga saat ini, narasi besar pertumbuhan merupakan wacana dominan yang paling sukses diekspor Barat ke negara-negara berkembang.
Selain ideologi pertumbuhan, Barat juga telah menawarkan resep pembangunan yang lain. Dalam hubungan ini, Nerfin melukiskan bahwa kecenderungan utopis dalam teori pembangunan mungkin paling tepat disimpulkan dalam konsep “pembangunan lain” yang dipopulerkan oleh laporan Dag Hammarskjold pada 1975, “What Now”, yang dipersiapkan pada kesempatan Sidang Khusus Ketujuh Sidang Umum PBB, dan diuraikan lebih lanjut dalam jurnal Development Dialog.[7] Menurutnya, “pembangunan lain” harus diorientasikan pada beberapa hal berikut:
· Berorientasi pada kebutuhan (ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan nonmaterial.
· Bersifat endogen (berasal dari sanubari tiap masyarakat, yang berdaulat menentukan nilai serta visi masa depannya).
· Bersifat mandiri (berarti bahwa setiap masyarakat pada dasarnya mengandalkan kekuatan dan sumber daya sendiri dalam artian kekuatan anggotanya serta lingkungan alam dan lingkungan budayanya).
· Secara ekologis baik (memanfaatkan secara rasional sumber daya lingkungan hidup dengan kesadaran penuh akan potensi ekosistem lokal dan juga batas global dan lokal yang dibebankan pada generasi masa kini dan generasi masa depan).
· Berdasarkan transformasi struktural (untuk merealisasikan persyaratan swakelola dan partisipasi dalam pengambilan keputusan oleh semua yang dipengaruhi keputusan tersebut, mulai dari komunitas pedesaan atau urban sampai dunia secara keseluruhan, tanpa ini tujuan di atas tidak dapat tercapai)
Senada dengan itu, Olle Tornquits juga mengusulkan untuk menjungkir-balikkan paradigma pembangunan dalam konteks politik. Menurutnya, kemunduran terbesar berbagai studi pembangunan yang menjadi arus utama adalah kurangnya dasar empiris di Dunia Ketiga, bias pada model demokrasi yang didasarkan pada generalisasi atau bahkan grand theories universal, serta berfokus pada tataran elit. Sebaliknya, keunggulan ‘teknis’ dari paradigma pembangunan mungkin dapat membantu kita mengimbangi ketidakmungkinan untuk menghindari kecenderungan ke arah fragmentasi dalam studi Dunia Ketiga pada saat membangun basis empiris yang solid. Dengan perkataan lain, yang harus dilakukan –ketika ditemukan dasar empiris yang solid bagi aspek-aspek politik dan pembangunan di Dunia Ketiga— adalah memperluas studi pembangunan politik serta menjungkir-balikkan dasar empiris dan teoretisnya.[8]
Dalam tataran yang lebih implementatif, Tornquist menawarkan beberapa resep untuk langkah ‘penjungkir-balikkan’ itu. Pertama, kita harus memperluas kerangka itu bukan dengan dimulai dari isu-isu pembangunan politik yang sempit, melainkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih relevan mengenai peran politik ketika orang berusaha memperbaiki taraf hidup dan memanfaatkan sumber daya mereka. Kedua, kita seharusnya tidak lagi bertolak dengan generalisasi empiris yang didasarkan pada norma dan pengalaman Eropa dan Amerika Utara, melainkan lebih dengan temuan-temuan empiris dalam politik dan pembangunan Dunia Ketiga. Akhirnya, baru setelah itu kita perlu kembali ke Barat untuk mencari pengalaman yang mungkin dapat mencerahkan pemahaman kita tentang apa yang terjadi di Dunia Ketiga, namun juga menawarkan perspektif baru tentang Barat itu sendiri.[9]
Counter terhadap paradigma pembangunan juga mulai dilancarkan oleh para pengamat dan aktivis di negara-negara Dunia Ketiga. Terutama mereka-mereka yang mulai menyadari bahwa negaranya telah menjadi sapi perahan negara-negara maju. Transformasi struktural, tentu saja, bukan satu-satunya bagi pendekatan alternatif, tetapi orientasi transformasi ini ditentukan oleh muatan normatif yang semestinya bertumpu pada kerjasama yang tulus antara negara-negara maju dengan negara-negara Dunia Ketiga dengan lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap agenda pembangunan.
Mengemukanya perspektif hak asasi manusia dalam paradigma pembangunan memang tidak datang dengan serta-merta. Fenomena ini lahir dan hadir dari proses dinamik yang panjang. Peta wacana mengenai perspektif hak asasi manusia dalam pembangunan dapat dijumpai dalam beragam model perdebatan. Beberapa hal yang cukup fenomenal antara lain diakomodasinya hak-hak pembangunan dalam berbagai kovenan internasional, seperti dalam kovenan tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya serta kovenan tentang hak sipil dan politik. Dalam tataran yang lebih implementatif, Deklarasi Vienna, terutama pada poin 8 hingga 10 telah memberikan petunjuk yang jelas mengenai hubungan pembangunan dengan hak asasi manusia. Pokok-pokok pikirannya sebagai berikut[10]:
· Demokrasi, pembangunan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi saling bergantung dan saling memperkuat. Demokrasi didasari oleh tekad suatu bangsa yang diekspresikan dengan bebas untuk menetapkan sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya mereka sendiri serta partisipasi penuh mereka dalam segala aspek kehidupan mereka. Dalam konteks tersebut di atas, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi pada tingkat nasional maupun internasional harus bersifat universal dan dilakukan tanpa terkait dengan syarat-syarat. Masyarakat internasional harus mendukung penguatan dan pemajuan demokrasi, pembangunan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan asasi di seluruh dunia.
· Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali bahwa negara-negara yang kurang berkembang, yang bertekad menjalankan proses demokratisasi dan perbaikan ekonomi, banyak di antaranya terdapat di Afrika, haruslah didukung masyarakat internasional agar mereka berhasil dalam melakukan transisi menuju demokrasi dan pembangunan ekonomi. Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia menegaskan kembali hak atas pembangun, seperti diterapkan dalam Deklarasi Hak atas Pembangunan, sebagai hak yang universal dan tidak dapat dicabut dan merupakan suatu bagian integral dari hak asasi manusia.
· Sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Hak atas Pembangunan, manusia adalah subyek utama dari pembangunan. Sementara pembangunan mendukung penerapan semua hak asasi manusia, tidak adanya pembangunan tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan pengurangan hak asasi manusia yang telah ditetapkan secara internasional. Negara-negara harus bekerjasama satu sama lain untuk menjamin berjalannya pembangunan dan mengatasi hambatan-hambatan dalam pembangunan. Masyarakat internasional harus mengembangkan kerjasama internasional yang efektif untuk mewujudkan hak atas pembangunan serta menghapuskan hambatan-hambatan dalam membangun. Agar kemajuan dalam penerapan hak atas pembangunan dapat terus berlanjut, dibutuhkan kebijakan pembangunan yang efektif pada tingkat nasional, maupun hubungan ekonomi yang adil serta lingkungan ekonomi yang menguntungkan pada tingkat internasional.
Keharusan HAM Menjadi Acuan Pembangunan
Umumnya para pakar Eropa berpendapat bahwa HAM mulai dikenal sejak lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Charta antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut menjadi dibatasi kekuasaannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban di muka umum. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak kebal hukum lagi dan mulai bertanggung jawab kepada hukum. Sejak itu mulai dipraktekkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan harus mempertanggungjawabkan kebijakasanaannya kepada parlemen. Dengan begitu kekuasaan raja mulai dibatasi. Hal ini merupakan embrio bagi lahirnya monarkhi konstitusional yang berintikan kekuasaan raja sebagai simbol belaka. Magna Charta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkret dengan lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul adagium yang intinya adalah bahwa manusia sama di muka hukum (equality before the law). Konsepsi ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi karena Bill of Rights mempromosikan asas persamaan.[11]
Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Roesseau dan Montesqueu tentang teori kontrak sosial dan trias politika yang mengedepankan pemisahan kekuasaan untuk menghindari tirani. Dalam deklarasi tersebut dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir, ia harus dibelenggu. Selanjutnya pada tahun 1789 lahir pula The French Declaration, dimana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasar The Rule of Law. Prinsip ini antara lain menyatakan bahwa tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa
Narasi besar persoalan hak asasi manusia sejatinya merupakan bagian inhern dari sejarah kemanusiaan itu sendiri. Namun demikian, hakikat dignitas kemanusiaan seringkali menjumpai realitas yang berbeda atau bahkan berlawanan dengan apa yang semestinya. Geoffrey Robertson melukiskan bahwa hak asasi manusia merupakan sesuatu yang menonjol dalam filsafat, namun dibutuhkan politisi, propagandis, dan revolusioner yang sesungguhnya untuk memberinya kekuatan hukum. Karena pada kenyataannya, meskipun manusia dilahirkan bebas namun seperti yang ditemui Rousseau, dimana-mana mereka berada dalam belenggu.[13]
Dengan mengutip pernyataan Thomas Jefferson, lebih jauh Geoffrey menyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama. Mereka dilimpahi oleh penciptanya sejumlah hak-hak yang tak dapat dicabut. Hak-hak tersebut antara lain meliputi kehidupan, kebebasan, dan hak untuk mencapai kebahagiaan. Untuk mengamankan hak-hak ini, pemerintahan yang dibangun, menjalankan kekuasaan-kekuasaanya secara adil dengan persetujuan mereka yang diperintah. Jika pemerintah kemudian merusak tujuan-tujuan tersebut, maka rakyat berhak untuk menggantikan atau menghilangkannya. Pemerintah baru yang ditegakkan harus meletakkan fondasinya di atas prinsip-prinsip hak asasi tersebut. Penyelenggara kekuasaannya harus menjunjung hak-hak tersebut, sehingga rakyat dapat merasakan keamanan dan kebahagianya.[14]
Dalam teori kontrak sosial disebutkan bahwa setiap warga membuat ‘persekutuan’ untuk melahirkan sebuah negara. Persekutuan adalah ketika orang menyerahkan kebebasannya untuk bergabung dalam suatu badan politik. Ini berarti bahwa kebebasan yang telah diserahkan akan dipertahankan dan dilindungi oleh negara. Tujuan dari persekutuan ini adalah untuk kepentingan publik. Negara tidak akan pernah bisa memiliki hak untuk menghancurkan, memperbudak atau secara sengaja memiskinkan warganya. Jika itu yang terjadi, maka warga negara berhak melakukan revolusi, menghancurkan persekutuan tersebut dan melakukan negosiasi ulang.[15]
Karena itu, proses pembangunan sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki kualitas hidup warga harus senantiasa diorientasikan pada penghormatan atas hak-hak dasar kemanusiaan. John Locke dapat dianggap sebagai pemikir pertama yang mengedepankan prinsip bahwa dalam merumuskan berbagai kebijakan, pemerintah harus melalui persetujuan rakyat dan komitmen negara haruslah dalam rangka melindungi kebebasan. “Manusia pada hakekatnya bebas, sama, dan independen. Tak seorang pun dapat dikeluarkan dari keadaan ini dan tunduk kepada kekuasaan politik dari orang lain tanpa persetujuannya. Satu-satunya cara, seseorang menyerahkan kebebasan alamiahnya dalam persekutuan masyarakat/warga negara adalah bersepakat dengan orang lain untuk bergabung dan bersatu dalam suatu komunitas. Tujuannya, demi penghidupan yang nyaman, aman, dan berdamai satu dengan yang lainnya dalam suasana yang aman atas harta miliknya.[16]
Namun demikian, dalam tataran tertentu, pembangunan justru menjadi agenda perusak nomor satu. Karena pada kenyataannya, agenda pembangunan seringkali tidak dibuat sesuai skenario yang dibutuhkan rakyat, Sebaliknya, pembangunan lebih merupakan ideologi yang dipaksakan negara sehingga kehadirannya justru banyak merenggut hak-hak dan kedaulatan rakyat. Karena itu, agar wajah pembangunan tidak tampak liar dan menakutkan, diperlukan perubahan paradigma dengan mengedepankan HAM sebagai salah satu dimensi penting yang wajib menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan agenda pembangunan. Sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Hak atas Pembangunan bahwa manusia harus menjadi subyek utama dari pembangunan. Begitu pun sebaliknya, aktivitas pembangunan sudah semestinya mendukung penerapan semua hak asasi manusia secara paripurna.
Pembangunan Berbasis HAM dalam Konstelasi Politik Indonesia
Pembangunan sebagai kompleks gagasan dan pandangan merupakan fenomena yang relatif baru. Ia terkait dengan tahapan-tahapan sejarah bangsa. Dalam konteks
Lebih rinci lagi, Dawam Rahardjo menyebutkan, bahwa kata pembangunan tidak jatuh dengan sendirinya secara tiba-tiba, ia dihidupkan kembali selama tahun 70-an. Sebagai istilah baru dengan kandungan kontekstual baru, istilah pembangunan pada mulanya dipahami secara sempit. Dalam perkembangannya, istilah pembangunan mengandung arti yang berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan orang yang memahaminya. Konsep pembangunan lebih dipamami seperti yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam hal ini kegiatan pemerintah yang membentuk pemahaman rakyat. Masyarakat lapisan bawah dapat menafsirkan dalam suatu pemikiran yang sederhana, seperti pembangunan jembatan, pembangunan jalan, bendungan, jaringan irigasi, gedung-gedung, dan pembangunan sarana-sarana fisik lainnya. Masyarakat kelas menengah dengan agak luas menafsirkan pembangunan ini hampir hanya sebagai pembangunan ekonomi. Setelah mengalami proses yang agak panjang dari evolusi pemahaman dan juga sebagai akibat dari program-program pembangunan itu sendiri yang dilakukan oleh pemerintah sekarang pembangunan dipahami pada hakikatnya sebagai “pembangunan sosial manusia”. Penekanan pengertian baru ini untuk menunjukkan bahwa usaha-usaha yang dilakukan pemerintah tidak hanya menyangkut penyediaan benda-benda materil tetapi juga menyangkut pemberdayaan kultural dan spiritual.[18]
Istilah pembangunan sebagai fenomena sosial, pertama kali diperkenalkan oleh Mohammad Hatta sebagai usaha untuk memobilisasi masyarakat dalam rangka memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan upaya bagi pembentukan masyarakat baru. Dalam menafsirkan pembangunan, Hatta lebih menekankan pada “usaha bersama” oleh seluruh masyarakat. Pandangan Hatta dalam hal ini mencerminkan ide yang populis. Namun demikian, dalam kenyataannya, hal ini tetap saja elitis, karena rakyat tetap saja sebagai objek mobilisasi politik oleh kaum intelektual melalui persuasi ideologis.
Secara paradigmatis, negara-negara berkembang pada umumnya —termasuk
Menurut Mubyarto, sebenarnya sejak terjadinya peristiwa “Malari” (Malapetaka Limabelas Januari) 15 Januari 1974, slogan Trilogi Pembangunan sudah berhasil dijadikan “teori” yang mengoreksi teori ekonomi pembangunan yang hanya mementingkan pertumbuhan. Trilogi pembangunan terdiri atas stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Namun sayangnya slogan yang baik ini justru terkalahkan karena sejak 1973-1974 selama 7 tahun Indonesia di”manja” bonansa minyak yang membuat bangsa Indonesia “lupa daratan”. Rezeki nomplok minyak bumi yang membuat Indonesia kaya mendadak telah menarik minat para investor asing untuk ikut “menjarah” kekayaan alam Indonesia. Serbuan para investor asing ini ketika melambat karena jatuhnya harga minyak dunia, selanjutnya dirangsang ekstra melalui kebijakan deregulasi (liberalisasi) pada tahun-tahun 1983-1988.[19]
Mubyarto juga menilai bahwa kebijakan penarikan investor yang menjadi sangat liberal ini tidak disadari bahkan oleh para teknokrat sendiri sehingga Radius Prawiro pada saat itu pernah mengaku ‘kecolongan’ dengan menyatakan “Dalam keadaan yang tidak menentu ini pemerintah mengambil tindakan yang berani menghapus semua pembatasan untuk arus modal yang masuk dan keluar. Undang-undang Indonesia yang mengatur arus modal, dengan demikian menjadi yang paling liberal di dunia, bahkan melebihi yang berlaku di negara-negara yang paling liberal”.[20]
Namun demikian,
Logika terbalik dalam statemen Soeharto tersebut tentu sangat menggelikan karena menempatkan pembangunan sebagai tujuan.[22] Ironisnya, setahun sebelumnya Soeharto telah menandatangani Kepres No.50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 4b Kepres ini dengan tegas disebutkan bahwa HAM harus menjadi pijakan bagi kegiatan pembangunan. Kalimat bersayap yang disampaikan Soeharto juga menyiratkan kecurigaan yang mendalam sekaligus mengonfrontasikan pembangunan di satu sisi dengan HAM di sisi yang lain. Padahal, perlindungan dan penghormatan HAM telah menjadi bagian integral dari tujuan awal pendirian bangsa ini.
Semangat reformasi sungguh telah membawa angin segar bagi kehidupan sosial-politik di tanah air. Dalam bidang HAM, Komnas HAM mencatat beberapa perkembangan positif, antara lain telah disepakatinya Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sebagai pelaksanaan amanat Tap MPR No.V/MPR/2000 dan pasal 47 UU 26/2000, telah dimulainya proses pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob), 1966 dan kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Sipol), 1966 oleh Pemerintah, penyusunan RUU tentang perlindungan Korban dan Saksi yang diprakarsai oleh DPR, dan telah diajukannya RUU Menentang Diskriminasi Rasial dan Etnis kepada DPR oleh kalangan masyarakat, serta telah siapnya RUU tentang Perlindungan Buruh Migran untuk dibahas oleh DPR. Kebijakan pemerintah dalam pemajuan hak-hak politik pantas disambut baik.[23] Selain itu, diakomodasinya HAM dalam amandemen UUD 1945 juga merupakan catatan yang melegakan.[24]
Namun demikian, evaluasi Komnas HAM tersebut juga menyisakan berbagai keprihatinan yang cukup mendasar. Belum berhasilnya Pemerintah mengatasi krisis ekonomi yang berlangsung sejak 1997, dampak globalisasi, dan dampak praktik korupsi telah mengakibatkan hak ekonomi-sosial-budaya serta hak-hak sipil dan politik dari sebagian besar bangsa ini tidak terpenuhi secara memadai. Karakteristik pembangunan
1. Menguatnya rezim modal global
Dunia kini ibarat sebuah kampung! Masihkah negara berperan mengayomi rakyatnya ketika dominasi modal-global berhasil menancapkan kuku-kukunya? Bersamaan dengan krisis keuangan di negara-negara Dunia Ketiga, paham neo-liberalisme dengan sadar didesakkan menjadi kebijakan badan-badan multilateral dunia seperti IMF, World Bank, dan WTO. Pasar bebas kemudian diciptakan menjadi perangkap untuk menerkam negara-negara miskin dengan lilitan dan jebakan utang yang secara sengaja diciptakannya. Pasar bebas memang bukan sebuah konsep netral, tapi lebih merupakan wajah lain dari kapitalisme dimana globalisasi diideologisasi menjadi kredonya.[25]
Elizabeth Martinez dan Arnold Garcia mencatat beberapa poin penting yang menjadi karakter utama neo-liberalisme.[26] Pertama, mekanisme pasar bebas dimana perusahaan-perusahaan swasta dibebaskan dari segenap keterikatan dan intervensi pemerintah. Mekanisme ini pada akhirnya akan menghilangkan kontrol negara terhadap mekanisme pasar sehingga harga sepenuhnya didasarkan atas kebebasan total dari gerak modal, barang dan jasa. Kedua, mereduksi pengeluaran negara, terutama anggaran publik dalam hal pelayanan sosial, seperti subsidi pendidikan, kesehatan, jaringan pengaman sosial, subsidi BBM, dan lain-lain. Ketiga, melakukan deregulasi dengan menekan peraturan-peraturan pemerintah agar menguntungkan kalangan pengusaha. Keempat, privatisasi dalam bentuk penjualan aset-aset publik seperti BUMN kepada investor swasta. Termasuk aset-aset strategis seperti bank, listrik, jalan tol, rumah sakit, dan bahkan barang yang menjadi public goods seperti air minum. Kelima, sebagai konsekuensinya, rakyat kehilangan akses terhadap barang publik yang sesungguhnya merupakan hak-milik komunitas.
Dengan skema kebijakan seperti itu, aktivis ICRP Trisno S. Sutanto menilai arus globalisasi neo-liberal merupakan perluasan kekuasaan segelintir pemodal yang mau mencaplok seluruh pelosok dunia di bawah kendali mereka. “Fenomena globalisasi yang sangat kompleks itu merupakan penciptaan kampung global tetapi sekaligus juga penjarahan secara global,” ungkapnya.[27] Menurut aktivis HAM Asmara Nababan, pengabdian negara pada kepentingan modal-global bahkan akan memicu kekerasan modal (capital violence) yang menindas rakyat dengan menjadikan ‘pembangunan’ sebagai kedoknya.[28]
Namun, ironisnya, pemerintah
Senada dengan itu, aktivis BINA DESA, Syaiful Bahari, menilai fenomena tersebut sebagai bentuk kekonyolan pemerintah. Memang yang diharapkan kapitalisme global adalah berkurangnya peran negara, melemahkan peran negara agar mereka bisa menguasai perekonomian. Sementara negara hanya diperlukan keberadaannya sebatas menjadi backing pengusaha semata.[30]
Menurutnya, pemerintah tidak punya keberanian untuk memberikan proteksi terhadap kepentingan masyarakat. Padahal, salah satu tugas negara adalah melindungi rakyatnya dari intervensi asing. Namun yang terjadi sekarang justru sebaliknya, semua diprivatisasi, semua diliberalisasi. “Kalau semua diprivatisasi, kalau semua diliberalisasi, buat apa ada negara? buat apa ada pemerintah ? Kita bubarin saja negara!,” tukasnya.[31] Keprihatinan yang sama juga disampaikan aktivis HAM Asmara Nababan. Ia melukiskan bahwa di saat kita memasuki era pasar bebas, yang akan menjadi korban akibat persaingan global adalah rakyat kecil. “Jika mereka tidak dilindungi dengan hukum yang melindungi HAM, lantas siapa yang akan melindungi mereka?”ujarnya.[32] Kerisauan semacam itu patut dimengerti karena terbukti banyak sekali kasus yang menunjukkan bahwa pemerintah lebih peduli pada kepentingan pemodal dari pada kepentingan rakyat.
2. Dominasi negara atas pembangunan
Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 Tahun 2005 yang ditetapkan pada tanggal 3 Mei 2005 lalu, secara resmi telah mengganti Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Munculnya Perpres ini telah direspon dengan beragam aksi masa di sejumlah daerah. Di Jawa Tengah, seluruh jaringan ornop yang dikoordinasi LBH Semarang dan Organisasi Tani Jawa Tengah (Ortaja) menyatakan menolak Perpres ini.[33] Aksi serupa juga dilakukan berbagai koalisi lembaga yang menolak Perpres itu di hampir seluruh provinsi. Bahkan, aktivis di provinsi Aceh yang masih berkabung pun tak ketinggalan turun ke jalan untuk menolak Perpres ini.
Dalam siaran persnya, Koalisi NGO-HAM Aceh menilai bahwa kebijakan Pemerintah mengeluarkan Pepres No 36 tahun 2005 tersebut semakin memperlihatkan ketidakpedulian Negara akan nasib rakyat miskin. Hak-hak kepemilikan atas tanah yang melekat pada masyarakat, tidak diakui oleh Perpres ini. Disatu sisi, semangat pembangunan untuk kepentingan umum merupakan sebuah langkah yang positif. Namun dalam pelaksanaannya, pendekatan pembangunan yang cenderung refresif masih dilakukan. Kehadiran Perpres ini, akan membawa implikasi, bahwa desain pembangunan dibuat berdasarkan aspirasi kelompok pemilik modal. Struktur politik seperti ini sama sekali tidak menguntungkan bagi kesatuan sosial masyarakat.[34]
Bagi Koalisi NGO HAM Aceh, kehadiran Perpres No. 36/2005 ini, merupakan bentuk dari penghianatan negara terhadap cita-citanya untuk menjunjung tinggi, menjamin dan memproteksi tegak-berdirinya Hak Asasi Manusia. Padahal, dalam UU No. 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 36 (ayat 2) disebutkan bahwa tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Dalam pasal 71 disebutkan bahwa pemerintah wajib bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM.
Namun demikian, meskipun tuntutan pencabutan Pepres No 36 Tahun 2005 itu demikian massif, pemerintah sepertinya tidak bergeming untuk tetap melaksanakan Pepres tersebut. Di beberapa tempat, bahkan, upaya untuk mempertahankan Pepres itu ditempuh secara emosional dan represif. Dalam Perpres tersebut sangat kuat nuansa bahwa presiden bisa mencabut hak atas tanah warga. Muatan hukum ini sangat meresahkan warga karena di masa lalu sejumlah pembebasan tanah untuk pembangunan berakhir dengan konflik. Penerapan Keppres No 55/1993 banyak menghasilkan perselisihan atau konflik antara pemilik tanah dan pihak yang akan membebaskan tanah.
Berdasarkan data sementara yang dihimpun oleh UPC, untuk wilayah Jabodetabek saja ada ratusan ribu jiwa yang ternacam menjadi korban penggusuran akibat dikeluarkannya Perpres No. 36/2005. Beberapa daerah yang sudah berhasil diidentifikasi adalah:
- + 4000 KK (12.000 jiwa) di kolong tol, Penjaringan, Jakarta Utara.
- + 10.000 KK (30.000 jiwa) di Muara Baru, Jakarta Utara. Terancam menjadi korban normalisasi Waduk Pluit.
- + 500.000 jiwa di 13 Kelurahan : proyek BKT; Cipinang Besar Selatan, Cipinang Muara, Pondok Bambu, Duren Sawit, Pondok Kelapa, Malaka Jaya, Malaka Sari, Pondok Kopi, Pulo Gebang, Ujung Menteng, Cakung Timur, Rorotan, Marunda.
- + 1.231.976 jiwa di 5 kecamatan dan kampung-kampung, korban proyek reklamasi Pantura : Wilayah Penjaringan : Batang, Muara Baru, Muara Angke, Kp. Kuar (317.950 jiwa); Cilincing : Kp. Si Pitung, Kali Baru, Marunda (26.793 jiwa); Tanjung Riok (398.277 jiwa), Pademangan (139.212 jiwa), Koja (349.744 jiwa).
- Puluhan kampung di Manggarai-Jatinegara-Cakung-Bekasi (1.700 KK), terkena proyek double-double track (rel kereta).
- 34 pemukiman tidak bersertifikat lain di Jakarta, versi Pemda DKI Jakarta.[35]
Ahli Hukum pertanahan, Maria Sumardjono menilai bahwa pengaturan pencabutan hak atas tanah melalui Perpres 36/2005 tidak memenuhi kaidah hukum karena materi muatannya menyangkut hak asasi manusia yang diatur melalui UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Padahal, UU HAM Pasal 36 ayat 1 menyebutkan dengan jelas bahwa setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum. Ayat 2 menyebutkan bahwa tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Serta ayat 3 menyebutkan bahwa hak milik mempunyai fungsi sosial.[36]
Senada dengan itu, Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara menilai bahwa Perpres itu bertentangan dengan sejumlah undang-undang. Menurutnya, isi Perpres No.36/2005 bersifat diskriminatif karena tidak mencerminkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat. “Sangat disesalkan, Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat tidak peka terhadap hal-hal seperti ini. Ia malah mengeluarkan aturan yang substansinya lebih buruk dibandingkan peraturan sebelumnya. Karena itu Komnas HAM berpendapat Perpres ini harus dicabut,” kata Abdul Hakim.[37]
3. Rendahnya akses dan partisipasi publik
Jika pembangunan dipandang sebagai upaya sadar untuk memperbaiki kualitas kehidupan rakyat, maka partisipasi publik merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan sehingga kegiatan pembangunan benar-benar dapat mendorong terciptanya transparansi dan good governance. Sherry Arnstein menyebutkan bahwa kontrol warga (citizen control) merupakan tingkat tertinggi partisipasi publik dimana rakyat memiliki kewenangan untuk memutuskan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan sumber daya dalam pembangunan.[38] Keharusan partisipasi publik ini menurut Longgena Ginting merupakan sesuatu yang logik, karena pada kenyataaannya rakyat merupakan pihak pertama dan “korban utama” yang paling banyak dirugikan akibat dampak pembangunan.[39] Karena itu, sudah sewajarnya jika pemerintah melakukan konsultasi publik terlebih dahulu sebelum melakukan suatu proyek pembangunan.
Ginting menyarankan agar pemerintah menggunakan pendekatan right-base approch dalam melaksanakan pembangunan dimana hak-hak asasi warga menjadi pertimbangan utama yang harus dikedepankan. Karena itu, jika pemerintah akan melakukan aktivitas pembangunan, misalnya membuat Taman Nasional, maka pelibatan masyarakat yang ada di sekitar itu menjadi penting. Tidak boleh hanya karena alam harus dilindungi, masyarakat disingkirkan, dimarjinalkan, bahkan dimiskinkan karena aksesnya diputus terhadap sumber daya alam yang ada di situ. Penetapan kawasan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) melalui SK Nomor 234/MENHUT-II/2004 tertanggal 4 Mei 2004 merupakan contoh nyata kesewenang-wenangan pemerintah. Keputusan pemerintah seperti itu tentu saja sangat tidak demokratis karena dinilai tidak terbuka dan sama sekali tidak melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Pendekatan right-base approch ini sekaligus merupakan upaya untuk melawan mainstream pembangunan yang ada yang cenderung memarjinalkan manusia dan lingkungannya demi pertumbuhan ekonomi. “Karena sejatinya pembangunan itu untuk kehidupan manusia dan oleh karena itu kepentingan manusia yang harus diutamakan. Kehidupan itu merupakan hak asasi yang tak bisa ditawar,” ujarnya.[40]
Buruknya apresiasi pemerintah terhadap partisipasi publik merupakan salah satu temuan penting Penelitian Demos mengenai Konteks dan Proses Demokratisasi Pasca Orde Baru (2003-2004). Dalam hubungannya dengan partisipasi publik, kualitas keterbukaan, musyawarah publik, serta akuntabilitas pemerintahan dan birokrasi, dapat disimak pada tebel-1. Fenomena ini sekaligus menunjukkan lemahnya indepedensi pemerintah dari campur tangan dan sub-ordinasi pihak-pihak luar serta lemahnya independensi kekuasaan pemerintah dari berbagai kepentingan di luar pemerintahan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Tabel-1:
Kualitas Hak dan Institusi Demokrasi yang berhubungan dengan partisipasi publik
| No | Hak dan Institusi (H/I) Demokrasi | Kualitas H/I Demokrasi | Perkembangan pasca 1999 | |||
| Baik | Buruk | [+] | [-] | [=] | ||
| 1 | Keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan terpilih di tingkat pusat dan daerah | 15 % | 85 % | 26 % | 26 % | 48 % |
| 2 | Keterbukaan dan akuntabilitas organ-organ eksekutif pemerintahan terpilih | 10 % | 90 % | 23 % | 27 % | 50 % |
| 3 | Desentralisasi politik dan pemerintahan yang dianggap paling sesuai bagi rakyat | 28 % | 72 % | 37 % | 20 % | 43 % |
| 4 | Musyawarah publik mengenai kebijakan pemerintahan, legislasi, dan pelayanan umum serta dukungan pemerintah pusat dan daerah menyangkut kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil | 24 % | 76 % | 38 % | 14 % | 48 % |
| 5 | Independensi pemerintah dari campur tangan dan subordinasi pihak-pihak luar | 31 % | 69 % | 12 % | 40 % | 48 % |
| 6 | Independensi kekuasaan pemerintah dari berbagai kepentingan di luar pemerintahan dalam rangka perlawanan terhadap berbagai bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan | 7 % | 93 % | 10 % | 43 % | 47 % |
Sumber: Riset DEMOS (2003-2004), data diolah
Dari keenam aspek partisipasi publik, kualitas keterbukaan, musyawarah publik, serta akuntabilitas pemerintahan dan birokrasi yang menjadi parameter kualitas hak dan institusi (H/I) demokrasi itu menunjukkan kualitas yang amat buruk. Demikian pula perkembangannya setelah tahun 1999 secara umum menunjukkan bahwa kualitasnya cenderung memburuk atau sama saja dari perkembangan sebelumnya. Karena itu, masalah partisipasi publik, keterbukaan, musyawarah publik, serta akuntabilitas pemerintahan dan birokrasi perlu mendapat perhatian yang memadai dalam peng-implementasian pembangunan.[41] Dengan begitu, program pembangunan dapat benar-benar menjadi ‘milik rakyat’ serta mampu menjawab persoalan dan harapan-harapan masyarakat secara nyata.
4. Terabaikannya hak-hak dasar rakyat
Rubrik Fokus dalam Harian Kompas membuat deskripsi secara detail mengenai fenomena kemiskinan paling kontemporer di negeri ini.[42] Ulasan Fokus ini antara lain menyebutkan bahwa pemerintah sudah semestinya merasa malu! Sudah membangun selama 60 tahun, dibekali wilayah yang sangat luas dan kaya sumber daya alam, iklim cuaca yang kondusif, tanah yang subur, dan selama puluhan tahun rajin berutang miliaran dollar AS ke berbagai negara dan lembaga internasional, kok bisa sampai rakyatnya mengalami busung lapar atau mati kelaparan. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan China, jumlah anak kurang gizi, angka kematian bayi, angka kematian ibu, anak putus sekolah, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, tingkat pendapatan, dan berbagai indikator kesejahteraan lainnya, lebih buruk. Bahkan dibandingkan Vietnam pun Indonesia kalah.
Merebaknya kasus busung lapar dan sejumlah penyakit lain yang diakibatkan oleh kemiskinan, juga menunjukkan kegagalan pemerintah memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan kesehatan sebagai hak paling dasar minimum rakyat. Meskipun tidak semua kasus malnutrisi adalah akibat faktor ekonomi, kasus busung lapar yang mengancam sekitar 1,67 juta atau delapan persen dari total anak balita di Indonesia diakui terkait erat dengan rendahnya daya beli dan akses masyarakat miskin ke pangan. Masih tingginya tingkat kelaparan di masyarakat menunjukkan ada yang tidak beres dengan kebijakan pembangunan. Secara normatif orientasi kebijakan pembangunan memang telah berubah. Pemenuhan hak dasar rakyat merupakan salah satu komitmen yang tertuang dalam Strategi Pembangunan Nasional 2004-2005.[43] Namun pada kenyataanya, implementasi kebijakan itu hingga sekarang sepertinya belum berubah dimana pembangunan masih menekankan pada pertumbuhan ekonomi, dengan mengabaikan pemerataan dan keadilan.
Strategi pembangunan yang ‘konservatif’ tersebut juga berimplikasi pada pilihan strategi penanganan kemiskinan yang konservatif pula. Meskipun Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) telah ‘berhasil’ merumuskan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SPKN), namun dalam tataran implementasinya tidak cukup signifikan menangani persoalan. Ini antara lain karena tidak sinkronya titik pandang dan dasar pijak yang dipakai. Pendekatan pertumbuhan dalam pengurangan kemiskinan, misalnya, masih begitu diandalkan pemerintah. Padahal, penyebab utama kemiskinan bukan karena kurangnya pendapatan, tetapi karena pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia serta ketidakmampuan negara untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi hak-hak demokratis warganya.
Hasil penelitian Demos memperlihatkan bahwa kualitas hak dan institusi demokrasi yang berhubungan dengan hak-hak dasar warga menunjukkan angka yang buruk. Demikian pula perkembangannya setelah Pemilu 1999 relatif sama buruknya. Tabel-2 berikut dapat menjelaskan keterpurukan dan terabaikannya hak-hak dasar rakyat.
Tabel-2:
Kualitas Hak dan Institusi Demokrasi berhubungan dengan hak-hak dasar rakyat
| No | Hak dan Institusi (H/I) Demokrasi | Kualitas H/I Demokrasi | Perkembangan H/I pasca 1999 | |||
| Baik | Buruk | [+] | [-] | [=] | ||
| 1 | Hak bekerja, jaminan sosial, dan kesehatan | 18 % | 82 % | 14 % | 59 % | 27 % |
| 2 | Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar | 36 % | 64 % | 28 % | 46 % | 25 % |
| 3 | Hak anak | 24 % | 76 % | 22 % | 54 % | 22 % |
| 4 | Kesetaraan dan akses yang adil | 13 % | 87 % | 13 % | 56 % | 31 % |
Sumber: Riset DEMOS (2003-2004), data diolah
Dalam penelitian lanjutan (Resurvey Demos, 2005), hak bekerja dan hak memperoleh jaminan sosial malahan semakin memburuk. Hal ini bahkan merupakan yang paling buruk diantara pemenuhan hak-hak yang lainnya. Hal ini dapat disimak pada tabel-3 berikut:
Tabel-3:
Kinerja dan cakupan beberapa hak dan institusi demokrasi
| No | Hak dan Institusi Demokrasi | Kinerja | Cakupan | ||||||
| Putaran 1&2 (2003-2004) | Mini Survey 2005 | Putaran 1&2 (2003-2004) | Mini Survey 2005 | ||||||
| + | - | + | - | + | - | + | - | ||
| 1 | Hak bekerja dan memperoleh jaminan sosial | 18 % | 82 % | 3 % | 97 % | 26 % | 73 % | 8 % | 92 % |
| 2 | Pemilu yang bebas dan jurdil | 48 % | 52 % | 45 % | 55 % | 55 % | 22 % | 47 % | 53 % |
| 3 | Sikap partai terhadap isu dan kepentingan vital | 18 % | 82 % | 3 % | 97 % | 29 % | 70 % | 5 % | 92 % |
| 4 | Kemampuan pemerintah untuk bebas dari pengaruh kelompok kepentingan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan | 10 % | 90 % | 11 % | 89 % | 25 % | 75 % | 18 % | 82 % |
| 5 | Partisipasi dan akses perempuan secara luas dalam urusan publik | 51 % | 49 % | 37 % | 63 % | 41 % | 59 % | 16 % | 84 % |
| 6 | Partisipasi dan konsultasi publik dalam perumusan dan penerapan kebijakan publik | 24 % | 75 % | 13 % | 87 % | 26 % | 73 % | 8 % | 92 % |
Sumber: Resurvey DEMOS (2005)
Tabel tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa pasca Pemilu 2004 dan selama berlangsungnya Pilkada 2005 beberapa hak dan institusi demokrasi tampak makin terabaikan. Parahnya kualitas kinerja serta cakupan hak dan institusi demokrasi ini terutama dalam hal “hak bekerja dan memperoleh jaminan sosial” (97%) serta “sikap partai terhadap isu dan kepentingan vital” (97%). Fenomena ini menunjukkan bahwa koneksitas antara rakyat dan partai –yang seharusnya menjadi agregator kepentingan rakyat— menghadapi masalah besar. Contoh paling telanjang adalah sikap DPR yang tanpa malu-malu mengusulkan kenaikan gaji dan berbagai tunjangan di tengah musibah busung lapar dan sejumlah persoalan lain yang melanda negeri ini.
Dengan menyimak fenomena tersebut, maka ajakan almarhum Mansour Fakih agar pemerintah —baik jajaran eksekutif maupun legislatif— menaruh perhatian yang besar terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat masih sangat relevan. Menurutnya, pemerintah harus terus diingatkan bahwa Deklarasi Wina 1993 menekankan tanggung jawab negara untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Peran aktif jajaran penyelenggara negara dalam melindungi dan memenuhi hak ekonomi-sosial-budaya harus ditindaklanjuti oleh para penyelenggara negara. Karena, merekalah yang memiliki kewenangan dalam menentukan alokasi sumber daya nasional. Penting kemudian untuk menyerukan agar pemerintah dan DPR-RI segera memanfaatkan substansi instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia sebagai sarana untuk melindungi hak asasi manusia kaum miskin.[44]
Penutup
Perubahan kedua UUD 1945 hasil amandemen telah mengakomodasi persoalan HAM secara cukup memadai. Bab XA yang secara spesifik mengintrodusir beragam item mengenai upaya-upaya pemajuan HAM secara normatif jauh lebih maju dari produk hukum yang ada sebelumnya. Namun yang menjadi masalahnya kemudian adalah sejak perubahan itu resmi diumumkan sepertinya belum tampak adanya perubahan signifikan dalam tataran implementasinya.
Salah satu contoh, misalnya, pasal 28H ayat 1 yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Idealitas normatif ini tampak begitu ‘mengawang-awang’ ketika kita menyaksikan penggusuran yang terjadi secara massif di berbagai tempat. Penggusuran jelas-jelas menunjukkan tidak terlindunginya hak bertempat tinggal para korban karena upaya ini seringkali dilakukan tanpa desain relokasi yang pasti.
Kesenjangan antara das sollen dengan das sein tampaknya akan menjadi “kondisi transisi” yang panjang atau bahkan akan terus berlangsung tanpa ujung manakala tanggung jawab perubahan diserahkan sepenuhnya pada aspek legal-formal semata. Karena itu, komplementasi strategi sangat dibutuhkan, misalnya dengan melakukan repolitisasi rakyat untuk memperkuat posisi tawar mereka sehingga mampu memperoleh hak-hak dasarnya secara semestinya.
Di tengah gemuruh perubahan yang kian tak pasti dan tak terkendali, desakan untuk melakukan repolitisasi rakyat memiliki urgensinya tersendiri. Terutama ketika pemerintah telah dengan semena-mena menyodorkan pembangunanisme sebagai model ideal yang absah dan titah yang tak bisa dibantah. Karena itu, tugas “suci” dari agen sosial yang melakukan repolitisasi rakyat adalah memberikan penyadaran dan sekaligus memastikan bahwa penghormatan atas hak asasi manusia –baik hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya maupun hak-hak sipil dan politik— memiliki posisi sentral dalam sebuah kebijakan pembangunan negara.***
Endnotes
ï Penulis bekerja sebagai peneliti DEMOS, Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi.
[1] Nisbet R (1999). Social Change and History, Oxford University, London.
[3] Streeten P (1983). “Development Dichotomies”, Discussion Paper 187, Institute of Development Studies, Sussex.
[5] Ibid.
[6] Arndt HW (1981) “Economic Development: a Semantic History”, Economic Development and Cultural Change 29 (3) (April).
[7] Nerfin M , ed (1997). Another Development: Approaches and Strategies, The Dag Hammarskjold Foundation, Uppsala.
[8] Olle Tornquist (1999). Politics Development A Critical Introduction, SAGE Publications, London, Thousand Oaks and New Delhi.
[9] Ibid.
[10] Vienna Declaration and Program Action ini disepakati dalam Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia, 25 Juni 1993.
[12] Ibid.
[13] Geoffrey Robertson (2000). Crimes Against Humanity: The Struggle for Global Justice, Penguin Book, London. Terjemahan oleh Suhartono, ed (2002). Kejahatan Kemanusiaan: Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global, Komnas HAM, Jakarta.
[14] Ibid.
[15] Ibid.
[16] John Locke (1690). “Second Treatise of Government: Of the Beginning of Political Society” in Geoffrey Robertson (2000). Crimes Against Humanity: The Struggle for Global Justice, Penguin Book, London.
[17] Dawam Rahardjo (1993). Islam dan Pembangunan: Agenda Penelitian Sosial di Indonesia, LP3ES, Jakarta.
[18] Ibid.
[19] JURNAL EKONOMI RAKYAT: Artikel - Th. I - No. 11 - Januari 2003.
[20] Radius Prawiro (1998). Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi: Pragmatisme dalam Aksi. Elexmedia, Jakarta.
[21] Simak: Suara Pembaruan, 24 Oktober 1994.
[22] Padahal, setahun sebelumnya Soeharto telah menandatangani Kepres No.50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasinal Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 4b Kepres ini dengan tegas disebutkan bahwa HAM harus menjadi pijakan bagi kegiatan pembangunan.
[23] Catatan Akhir Tahun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tentang Kondisi Hak Asasi Manusia Selama 2003.
[24] Dalam perubahan kedua Amandemen UUD 1945 HAM diposisikan dalam bab tersendiri, yaitu Bab XA mulai pasal 28A hingga pasal 28J.
[26] Elizabeth Martinez and Arnoldo Garcia “Wat is 'Neoliberalisme?” dalam http://squat.net/caravan/ICC-nl/globalisation-nl/neoliberalisme-nl.htm
[27] Disampaikan dalam seminar “Peran Agama-agama dalam Pembangunan” yang diselenggarakan ICRP dan MADIA di Jakarta, 18 April 2005.
[28] Asmara Nababan, “Tanpa Penghormatan dan Akuntabilitas Hak Asasi Manusia, Investasi Modal Adalah sebuah Kehancuran” dalam J. Anto dan Benget Silitonga (2004). Menolak Menjadi Miskin: Gerakan Rakyat Porsea Melawan Konspirasi Gurita Indorayon, Bakumsu, Medan.
[29] Andik Hardiyanto (2004) “Land Reform dan Kemiskinan Petani” dalam Daulat Rakyat Dasar Kebijakan Anti Pemiskinan, GAPRI, Jakarta.
[30] Wawancara dengan Syaiful Bahari, Jakarta: 17 Mei 2004.
[33] Dalam Siaran Pers No.066/LBHSmg/V/2005 aktfis ornop di Jawa Tengah menilai bahwa Perpres No.36 Tahun 2005 merupakan bukti keberpihakan pemerintah pada modal sekaligus merupakan wujud pengingkaran negara terhadap hak rakyat atas tanah.
[34] Siaran Pers Koalisi NGO HAM Aceh, 27 Juni 2005.
[35] Siaran Pers “Aksi Jaringan Rakyat Miskin Kota Tolak Perpres No.36 Tahun 2005” dalam http://www.urbanpoor.or.id
[38] Sherry Arnstein (1969) “A Ladder of Citizen Participation” dalam Bimo Nugroho “Partisipasi Rakyat Membuat UU”, Kompas: 1 Agustus 2002.
[39] Wawancara dengan Longgena Ginting, Jakarta: 14 Mei 2004.
[40] Ibid.
[41] Simak hasil penelitian Demos (2004) mengenai Masalah-masalah dan Pilihan-pilihan Demokratisasi di Indonesia.
[43] Ini dapat disimak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan pembangunan Nasional, Jakarta 12 Desember 2004.