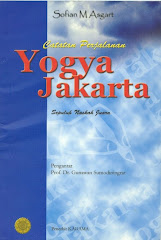Mentalitas Korupsi dan Dampaknya
Bagi Kehidupan Berbangsa
Sofian Munawar Asgart
Iftitah
Pemberantasan korupsi merupakan salah satu amanat dan sekaligus tuntutan yang kerap dikumandangkan sejak awal masa reformasi. Hal ini dinilai sebagai sesuatu yang urgen karena korupsi telah membawa dampak yang begitu buruk bagi kehidupan bangsa secara nyata. Karena itu wajar jika pemerintahan masa transisi pasca Orde Baru telah mengagendakan upaya yang cukup serius untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat yang begitu berambisi mengenyahkan praktik korupsi di negeri ini. Hal ini paling tidak dapat disimak dari aspek legal-formal dengan dikeluarkannya sejumlah peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan korupsi.
Selama masa pemerintahan BJ. Habibie, misalnya, tak kurang dari delapan produk hukum yang dirancang untuk menjaring para koruptor, meskipun ternyata tak satu pun yang efektif menuai hasil. Demikian pula pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati, peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi terus diproduksi. Namun tidak juga menurunkan nyali dan birahi para koruptor untuk melakukan korupsi. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun tidak mau ketinggalan. Pada awal masa pemerintahannya, SBY juga meluncurkan Inpres dan Keppres mengenai upaya pemberantasan korupsi. Akankah berbagai peraturan perundangan ini efektif untuk mengusir korupsi di negeri ini?
Tabel-1 Produk Hukum Mengenai Korupsi Pasca-Orde Baru
| No | Peraturan | Substansi |
| 1 | Tap MPR No.XI/ MPR/1998 | Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. |
| 2 | Inpres No.30/1998 | Instruksi Presiden kepada Jaksa Agung untuk segera memeriksa mantan Presiden Soeharto. |
| 3 | UU No.28/1999 | Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. |
| 4 | UU No.31/1999 | Pemberantasan Tindak Pemberantasan Korupsi. |
| 5 | PP No.65/1999 | Tatacara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara. |
| 6 | PP No. 66/1999 | Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan serta Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa. |
| 7 | PP No.67/1999 | Tatacara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa. |
| 8 | PP No.68/1999 | Tatacara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. |
| 9 | PP No.71/2000 | Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi. |
| 10 | UU No.20/2001 | Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti UU No.31/1999. |
| 11 | UU No.30/2002 | Tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. |
| 12 | UU No.25/2003 | Tentang Perubahan UU No15/2002 Tentang Tindak Pidana Anti Pencucian Uang. |
| 13 | Inpres No.5/2004 | Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. |
| 14 | Kepres No11/2005 | Pembentukan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. |
Rezim pemerintahan memang terus berganti. Seiring dengan itu, sejumlah peraturan pun terus diperbarui. Namun demikian, mentalitas korupsi hingga kini belum juga terkalahkan. Apa sejatinya korupsi itu? Apa pula akar masalah dan dampaknya bagi kehidupan berbangsa? Strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan ini? Adakah solusi alternatif yang efektif untuk memberantas korupsi? Melalui tulisan ini, penulis tidak berpretensi untuk menjawab segenap persoalan itu secara simultan, namun risalah kecil ini tetap diharapkan dapat memberi masukan yang signifikan bagi upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.
Definisi dan Redefinisi Korupsi
Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio yang berarti busuk atau rusak. Dalam padanan kata kerjanya, korupsi atau corrumpere juga dapat berarti menggoyahkan, memutar-balik, atau menyogok. Karena itu, Transparency International mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal berusaha memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari perspektif ini, perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi mencakup beberapa unsur, yaitu: a) melanggar hukum yang berlaku, b) penyalahgunaan wewenang, c) merugikan negara, d) memperkaya pribadi/diri sendiri.
Sosiolog Syed Hussein Alatas mendefinisikan korupsi sebagai penyalah-gunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Esensinya adalah bahwa korupsi merupakan pencurian yang dilakukan melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Sementara itu, Mark Phillip memberikan tiga definisi berdasarkan orientasinya, yaitu public office-centered, public interest-centered, dan market-centered. Definisi public office-centered memandang korupsi sebagai tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi. Definisi public interest-centered melihat korupsi sebagai perilaku yang merugikan kesejahteraan publik. Sedangkan definisi market-centered berdasar pada penggunaan metode ekonomi dalam analisis politik, dimana korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pegawai negeri untuk memperoleh pendapatan ekstra dari publik.
Secara legal-formal, UU No. 20/2001 Jo. UU No. 31/1999 mendefinisikan korupsi sebagai suatu tindakan yang melawan/melanggar hukum dengan menyalahgunakan kewenangan/kesempatan/sarana yang ada pada seseorang karena jabatan/kedudukannya (abuse of power) untuk memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi sehingga menimbulkan kerugian keuangan/kekayaan/perekonomian negara. Secara sepintas, definisi “formal” korupsi ini memang tidak tampak ada masalah. Namun menurut Taufik Abdulah, jika dikaji lebih cermat, ada sesuatu yang absurd dimana praktik korupsi “harus” melibatkan aparat negara dan merugikan keuangan negara sehingga jika praktik itu tidak merugikan dan melibatkan aparat negara maka tidak dapat dikategorikan sebagai korupsi.
Sejalan dengan itu, Dawam Rahardjo mengungkapkan bahwa sebagai konsep korupsi sebenarnya mempunyai makna generik yang sama dengan kolusi dan nepotisme (KKN). Ketiga konsep itu bermuara kepada pemahaman yang sama, yaitu menyangkut praktik penyalahgunaan kekuasaan (power) dan wewenang (authority), baik yang dilakukan oleh seseorang, atau sekelompok orang, untuk kepentingan diri sendiri, kelompok atau lembaga lainnya, sehingga merugikan kepentingan masyarakat luas atau publik. Oleh karena itu konsep kolusi dan nepoteisme juga berarti korupsi, karena dibalik praktik kolusi dan nepotisme berlangsung penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk menguntungkan diri dan kalangan sendiri, dengan mengorbankan kepentingan orang banyak.
JM. Wammey menyebutkan bahwa tidak semua korupsi mewujud dalam bentuk penyuapan (bribe) berupa uang. Sebagai contoh seseorang yang memiliki posisi yang berhadapan dengan kepentingan publik menggunakan waktu pelayanannya untuk kebutuhan pribadi, seorang pemimpin yang menggunakan aparat instansi atau kantor untuk digunakan atau dimanfaatkan secara pribadi. Dalam beberapa kasus terdapat kerancuan istilah antara penyuapan (bribe) dengan hadiah (gift). Dalam beberapa hal, kedua istilah tersebut dapat dibedakan dari sisi, penyuapan bersifat reciprocity sedangkan hadiah tidak. Sekalipun secara fundamental dapat dibedakan, namun kadang-kadang masih tetap menemui kesulitan untuk membedakannya. Sehingga muncul beberapa pertanyaan, apakah dengan demikian sebuah hadiah dapat berubah menjadi penyuapan? Apakah mengukur besarnya hadiah bisa dijadikan pembatas antara korupsi dan hadiah? Ataukah dapat dibedakan dari sisi cara pemberian yang terang-terangan atau yang bersifat tertutup? Mitos bahwa korupsi merupakan intrinsic nature sehingga tidak mungkin diukur, menyebabkan persoalan korupsi menjadi semakin rumit karena tipologinya juga kian beragam.
Dengan mengawinkan berbagai tipologi korupsi, George Junus Aditjondro menawarkan model tipologi “korupsi berlapis tiga”. Menurutnya, korupsi merupakan extra ordinary crime yang terkait beragam dimensi. Berikut tipologi korupsi yang diungkapkan Aditjondro:
Tabel-2 Tipologi Korupsi Berlapis Tiga
Korupsi Lapis Pertama | · Penyuapan (bribery), di mana prakarsa awal datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau penguasa pelayanan publik, atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara. · Pemerasan (extortiona), di mana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau petugas pelayanan publik lainnya. |
| Korupsi Lapis Kedua | Jejaring korupsi antara birokrat, politisi, aparat penegak hukum, dan perusahaan yang mendapatkan kedudukan yang istimewa. Biasanya ada ikatan yang bersifat nepotis di antara beberapa anggota jejaring korupsi, yang dapat berlingkup nasional. |
| Korupsi Lapis Ketiga | Jejaring korupsi berlingkup internasional, di mana kedudukan aparat penegak hukum dalam model korupsi lapis kedua digantikan atau berbarengan dengan lemaga-lembaga penghutang dan/atau lembaga-lembaga internasional yang punya otoritas di bidang usaha atau trans-national corporate (TNC) yang produknya ‘terpilih’ oleh pimpinan rezim yang jadi anggota jejaring korupsi internasional tersebut. |
Namun demikian, dalam memahami fenomena korupsi, sepertinya kita terlena pada tipologi “korupsi lapis pertama” dan kurang memberi perhatian pada tipologi korupsi lainnya. Ini antara lain tampak dalam terminologi yang dipilih secara legal-formal dalam peraturan perundang-undangan yang lebih menekankan pada pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kekuasaan secara ‘personal’ dengan melenakan jejaring korupsi yang bersifat sistemik, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. B. Herry Priyono melukiskan bahwa konsepsi korupsi yang diorientasikan semata-mata pada kiprah pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mengeruk rente dari sektor bisnis itu adalah konsep lama. Bahkan di negara-negara yang dikenal sebagai penyebar konsepsi seperti itu sedang berlangsung berbagai revisi, bukan hanya pada tataran gagasan, tetapi juga pada dataran kebijakan. Dalam hal ini, korupsi pasar (market corruption) merupakan gejala “baru” tipologi korupsi yang sudah amat meluas.
Menurutnya, fakta bahwa soal itu belum dianggap serius mungkin persis menunjukkan tertinggalnya kerja analisa kita dari gerak fakta. Karena itu, ia menambahkan bahwa meluasnya korupsi bukan semata-mata hanya karena malapraktik aparat pemerintah (administrative corruption), tetapi juga karena para pelaku bisnis (market corruption). Dalam kaitan dengan birokrasi pemerintah, kekuatan uang yang begitu besar di tangan pelaku bisnis, bahkan, dapat dipakai untuk membeli undang-undang, supervisi, serta “mengongkosi” seluruh jajaran pengadilan. Karena itu, sudah saatnya kita melakukan redefinisi terhadap tindak pidana korupsi. Dengan begitu, strategi pemberantasan korupsi dengan ragam solusi alternatifnya dapat diupayakan secara komprehensif.
Identifikasi Korupsi: Akar Masalah dan Dampaknya
Survey diagnostik atas tindak pidana korupsi yang dilakukan Partnership for Goverment Reform menyebutkan empat alasan utama yang menjadi penyebab terjadinya praktik korupsi. Keempat hal itu adalah rendahnya gaji (36%), kurangnya pengawasan (19%), buruknya moral (16%), dan lemahnya penegakan hukum (7%). Mengenai rendahnya gaji pegawai, Herbert Feith pernah melukiskan bahwa Dr. A. Halim, Perdana Menteri Republik Indonesia pada tahun 1950 menulis surat terbuka kepada Presiden Soekarno, dan menyatakan dengan tegas bahwa gaji pegawai yang hanya cukup membiayai hidup untuk dua minggu atau paling lama 20 hari, telah menyebabkan mereka rela menjual harga dirinya dan melibatkan diri dalam korupsi kecil-kecilan (minor corruption). Korupsi kecil-kecilan yang dibiasakan dan dibiarkan ini kemudian berkembang-biak dan lambat-laun menjadi jombi yang kini menghantui negeri ini.
Namun begitu, di mata antropolog Sjafri Sairin, membiaknya praktik korupsi lebih berkait erat dengan faktor mentalitas. Meskipun rendahnya gaji dapat dipahami sebagai salah satu alasan, namun menurutnya, praktik korupsi tidak berhubungan secara langsung dengan tinggi atau rendahnya tingkat penghasilan. Mereka yang terjerumus pada praktik korupsi adalah mereka yang memiliki mentalitas yang “selalu merasa kekurangan” (unsatiable mentality). Mereka sepertinya tidak pernah merasa puas dengan penghasilan yang telah diperoleh, walaupun menurut ukuran umum, sebenarnya penghasilan itu sudah cukup untuk menopang kehidupan mereka secara wajar. Keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak tidak pernah terpuaskan sehingga terkesan serakah. Untuk memuaskan “rasa kurang” itu mereka berusaha menempuh berbagai jalan, baik yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan etika, maupun yang berlawanan dengan itu. Inilah sikap yang disebut sosiolog Kuntjaraningrat sebagai “mentalitas menerabas”.
Sementara itu, budayawan Mudji Sutrisno menilai bahwa akar masalah munculnya praktik korupsi adalah akibat demoralisasi. Menurutnya, manusia pada dasarnya mempunyai kecenderungan dan niat untuk melakukan korupsi. Namun, bila moralitasnya bagus, ia tidak akan pernah melakukannya. Masalahnya sekarang adalah niat untuk korupsi ada, sementara sistem dan budaya serta lingkungan juga mendukung terciptanya praktik korupsi. Ia menambahkan bahwa munculnya demoralisasi pada tingkatan niat ini ditandai dua hal. Pertama, adanya hak milik kolektif. Bila seseorang menjadi penguasa atau pejabat publik atau bahkan menjadi diri sendiri sekalipun, dia lantas akan merasa memiliki semua. Apa yang seharusnya dikelolanya dengan tanggung jawab yang tinggi justru dijadikan hak milik baginya. Akibatnya, mereka tidak merasa harus bertanggung jawab secara moral terhadap apa yang dimilikinya tersebut. Kedua, moralitas yang tertanam dalam diri individu mengalami krisis. Ini ditandai dengan tidak adanya kesadaran dalam individu, apakah ia melakukan perbuatan baik atau tidak. Dengan kata lain, sense of goodder and sense of badder tidak tumbuh dalam diri individu sehingga ia tidak mengenali lagi apakah yang dilakukannya baik atau tidak. Akibatnya, tidak ada konsep moral dalam pekerjaannya. Hal inilah yang akhirnya merangsang munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme di semua lini kehidupan.
Stevanus Subagija menawarkan teori disonansi kognitif untuk mengkaji lebih dalam mengapa korupsi di Indonesia seolah masih terus dipertahankan. Menurutnya, teori yang dikembangkan Leon Festinger dan diperdalam oleh Albelson, McGuire, Newcomb, Ronsenberg, dan Tannenbaum dapat menjelaskan ihwal kegagalan memberantas praktik korupsi. Pemahaman, kesadaran dan pengertian (kognisi) seseorang mengenai dirinya sendiri dan dunianya (khususnya praktik korupsi) selalu berhubungan dengan tarik menarik antara dua kemungkinan yakni melakukan korupsi dan tidak melakukan korupsi. Seorang koruptor dan mereka yang terlibat langsung atau tidak, pendeknya kecipratan hasil korupsi dapat dipastikan mengalami tarik menarik sehingga terjadi “ketidak-seimbangan kognisi”. Di sinilah kuncinya bahwa kemungkinan besar korupsi di Indonesia masih dipertahankan, karena unsur-unsur kognisi tentang korupsi masih dianggap sebagai sesuatu yang lumrah atau bahkan dianggap sebagai tuntutan situasi, risiko jabatan yang temporer karena sudah menjadi fatsun urusan pemerintahan. Model seperti ini tampaknya telah sukses dipraktekan rezim Orde Baru dengan sempurna dan terwariskan hingga kini.
Namun demikian, apapun akar masalahnya, korupsi telah nyata-nyata menimbulkan dampak yang begitu buruk bagi kehidupan bangsa. Simon Saragih menyebutkan bahwa praktik korupsi merupakan kejahatan ekonomi yang sangat keji. Karena praktik korupsi telah menyebabkan perekonomian tidak berkembang sesuai aturan pasar, tidak ada kompetisi dan kemajuan dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada, tumpukan utang negara semakin meninggi secara spontan, proses pemiskinan masyarakat semakin mendalam, kredibilitas pemerintah di mata masyarakat semakin memburuk. Pada gilirannya, muncul pula lingkaran setan, sebuah situasi yang amat pelik untuk dipecahkan. Ekonom kenamaan, Kwik Kian Gie, menyatakan bahwa daya rusak korupsi telah menyebabkan bangsa ini kehilangan kemandiriannya. Ia bahkan bercerita tentang keterpurukan Indonesia sebagai negara kaya yang menjadi miskin akibat pemimpinya terjerumus ke dalam mental kuli yang koruptif. Menurutnya, Indonesia yang perut bumiya memiliki kandungan minyak sangat besar dibanding kebutuhan nasionalnya, setelah 60 tahun merdeka hanya mampu menggarap minyaknya sendiri sekitar 8 persen. Sisanya justru diserahkan kepada eksplorasi dan eksploitasi perusahaan-perusahaan asing melalui keputusan politik yang kolutif.
Dalam sebuah penelitiannya, Vinay Bhargava dan Emil Bolengaita mengungkapkan bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia jauh lebih buruk ketimbang di Korea dan Thailand. Dengan mengambil studi kasus di empat negara, Korea Selatan, Thailand, Filipina, dan Indonesia, kedua peneliti itu menyebutkan bahwa korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Korupsi juga dapat menghambat pembangunan ekonomi dan rentan sekali menambah kemelaratan warganya. Kedua peneliti itu juga mengingatkan bahwa, banyak negeri menjadi lumpuh karena lemahnya pengadilan dan kontrol masyarakat terhadap praktik korupsi yang menyengsarakan rakyat. Jeremy Pope bahkan menyebut korupsi itu sebagai “dosa publik”. Menurutnya, korupsi telah mengakibatkan kesengsaraan luar biasa yang diderita rakyat karena keputusan-keputusan penting diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pribadi tanpa memperhitungkan akibat-akibatnya bagi publik.
Begitu banyak kerugian yang mendera bangsa ini akibat praktik korupsi. Angin reformasi yang bertiup kencang, bahkan, tidak cukup kuat untuk menghalau praktik korupsi di negeri ini. Era reformasi justru telah turut mendorong desentralisasi korupsi yang mulai mewabah lewat otonomi daerah yang salah kaprah. Survey yang dilakukan The Habibie Center, misalnya, mengungkap lebih dari 20 modus korupsi di daerah mengiringi implementasi otonomi daerah. Dalam kondisi seperti ini, rakyat tentu semakin menderita akibat praktik korupsi yang makin nyata dengan jarak penghisapan yang lebih dekat dari kehidupannya. Tepatlah ungkapan yang dilontarkan Faisal Basri bahwa korupsi telah menjadi penyebab utama porak-porandanya sendi-sendi ekonomi yang mengakibatkan degradasi pondasi ekonomi yang paling parah.
Alternatif Solusi dan Strategi Pemberantasan Korupsi
Meskipun genderang perang terhadap kejahatan korupsi terus ditabuh, namun praktik haram yang memelaratkan rakyat ini seakan sulit untuk ditaklukkan. AE Priyono melukiskan bahwa dalam dasawarsa terakhir ini “prestasi” korupsi Indonesia belum juga berubah. Hasil survey Transparency International selama supuluh tahun terakhir ini setidaknya dapat dijadikan indikator tiadanya perubahan yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Organisasi nirlaba yang berpusat di Berlin ini memang terus-menerus menempatkan Indonesia di jajaran negeri-negeri terkorup di dunia.
Tabel-3 Peringkat Korupsi Indonesia
| Tahun | Indeks CPI | Peringkat |
| 1995 | 1,94 | 41 dari 41 negara |
| 1996 | 2,65 | 44 dari 54 negara |
| 1997 | 2,72 | 45 dari 52 negara |
| 1998 | 2,0 | 80 dari 85 negara |
| 1999 | 1,7 | 96 dari 99 negara |
| 2000 | 1,7 | 85 dari 90 negara |
| 2001 | 1,9 | 88 dari 91 negara |
| 2002 | 1,9 | 96 dari 102 negara |
| 2003 | 1,8 | 128 dari 133 negara |
| 2004 | 2,0 | 135 dari 145 negara |
Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Teten Masduki, pernah merasa frustrasi melihat fenomena korupsi Indonesia yang begitu menggurita. Namun kemudian ia menyadari bahwa bersikap pasrah dan menyerah sama saja dengan menggadaikan kedaulatan kepada koruptor. Karena itu, menurutnya, tak ada pilihan lain dalam menghadapi kejahatan korupsi selain melawannya. Hal yang sama juga pernah dikemukakan Ketua Transparency International, Peter Eigen. Ia mendapatkan contoh dari banyak negara yang awalnya memperlihatkan praktik korupsi akut, suatu kondisi yang sudah tanpa harapan, namun juga bisa berubah. Karena itu berkali-kali ia menyarankan agar jangan pernah menyerah dalam memberantas korupsi. Persoalannya kemudian adalah bagaimana menyiapkan strategi yang efektif sehingga penyakit endemik korupsi benar-benar dapat diatasi.
John ST Quah, peneliti kebijakan publik dan korupsi dari National University of Singapore (NUS), mengatakan bahwa kunci sukses penanganan korupsi terletak pada dua unsur penting. Pertama, komitmen yang kuat dari presiden atau petinggi negara. Kedua, tersedianya instrumen dan aturan perundang-undangan yang baik. Menurut Quah, strategi paling efektif untuk menanggulangi korupsi adalah mengombinasikan komitmen pemimpin politik yang kuat dengan perangkat instrumen yang memadai. Kombinasi dari dua unsur ini dapat disimak pada matriks berikut.
Tabel-4 Matriks Strategi Penanggulangan Korupsi
| | Instrumen Memadai | Instrumen Tak Memadai |
| Komitmen Kuat/Tinggi | Strategi Efektif | Strategi Tak Efektif 2 |
| Komitmen Lemah/Rendah | Strategi Tak Efektif 1 | Strategi Tanpa Prospek |
Quah juga menambahkan bahwa strategi penanggulangan korupsi harus diiringi dengan upaya untuk meminimalisasi sebab-sebab munculnya tindak pidana korupsi. Karena korupsi antara lain disebabkan oleh adanya insentif dan kesempatan untuk melakukan tindakan korup, maka strategi komprehensif untuk menanggulangi korupsi di sebuah negara harus mengikuti “the logic of corruption control”. Artinya, logika pengendalian korupsi harus didesain untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan insentif dan kesempatan yang menjadikan korupsi menjadi sebuah godaan tak tertahankan. Namun demikian, parameternya tentu berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Pilihan strategi penanganan korupsi akan sangat tergantung dari tingkat endemik korupsi di suatu negara. Lantas, adakah strategi spesifik yang dapat ditempuh dalam penanggulangan korupsi di Indonesia?
Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) melalui milinglist-nya pernah mengakomodasi beragam ide dengan melakukan inventarisasi “Kumpulan Tulisan Mengenai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia”. Sebagai sebuah ruang terbuka, masukan dan tawaran yang mengemuka dalam milis itu tentu sangat beragam. Mulai dari usulan ‘sepele’ yang bersifat guyon hingga tawaran strategi yang didasarkan atas hasil riset yang serius dan mendalam. Dari sekian banyak tawaran solusi yang mengemuka, secara simplikatif, ada lima hal yang dapat ‘dikategorisasi’ sebagai langkah paling mendesak yang dapat dijadikan alternatif solusi dan strategi pemberantasan korupsi, yaitu: reformasi birokrasi, penegakan hukum, perbaikan aturan perundang-undangan, pemberdayaan lembaga anti-korupsi, serta pelibatan masyarakat luas dalam pengawasan dan pemantauan korupsi. Lima hal inilah yang selanjutnya akan menjadi titik pijak dalam membahas alternatif solusi dan strategi pemberantasan korupsi.
1. Reformasi birokrasi
Ajakan untuk melakukan cleaning house police yang dilontarkan SBY seiring pembentuakan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtastipikor) disambut positif oleh banyak kalangan. Hal ini mengindikasikan keseriusan pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi sebagai salah satu pilar penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun sayangnya, himbauan ini tidak disambut secara serius oleh birokrasi di bawahnya, baik di departemen-departemen, BUMN/D, maupun birokrasi di tingkat lokal. Ini terbukti dari masih lambannya berbagai pelayanan publik. Bahkan, birokrasi perizinan bisnis pun masih amat panjang dan penuh pungli.
Survei yang dilakukan Transparency International terhadap 1.305 pebisnis, misalnya, menyebutkan bahwa mereka masih tetap harus memberi uang pelicin saat berhubungan dengan instansi pelayanan publik. Hal ini mengindikasikan secara jelas bahwa birokrasi pelayanan publik masih menjadi sarang korupsi suap. Para pebisnis mengaku kebanyakan melakukan interaksi korupsinya dengan pihak Bea Cukai (62%), Kepolisian (56%), TNI (49%), dan Lembaga Peradilan (48%). Sementara itu, Jakarta dan Surabaya –sebagai pusat bisnis- juga tercatat sebagai pemda terkorup. Fenomena ini menyiratkan bahwa upaya untuk melakukan reformasi birokrasi perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Karena sistem pelayanan publik masih sangat birokratis, maka reformasi birokrasi merupakan syarat mutlak untuk memberantas korupsi.
Dalam hal reformasi birokrasi, sejatinya kita punya beberapa contoh eksperimentasi yang berhasil. Salah satunya yang layak dikemukakan adalah “gebrakan” yang dilakukan Gamawan Fauzi, mantan Bupati Solok yang kini menjadi Gubernur Sumatera Barat. Ia dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan merakyat. Sebagai pejabat pemerintah, Gamawan tidak pandang bulu dalam mengambil tindakan bagi aparatnya yang indisipliner, bahkan terhadap sahabatnya sendiri. Dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungannya serta menerapkan larangan menerima dan memberi suap, ia berani mengambil langkah yang tegas terhadap bawahannya, yakni dengan menurunkan pangkat 23 stafnya, menunda kenaikan pangkat 9 orang pegawainya, bahkan memberhentikan 10 pegawai. Atas upayanya itu ia menerima Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA).
2. Penegakan hukum
Koordinator Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB), Saldi Isra, menilai bahwa penegakan hukum merupakan kunci terpenting dari upaya pemberantasan korupsi saat ini. Menurutnya, ketika berbagai peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi telah banyak diproduksi, maka problem berikutnya adalah pada tingkat aparaturnya. Karena itu, diperlukan orang yang benar-benar punya komitmen kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi sesuai cita-cita hukum tanpa pandang bulu.
Dalam hal penegakan hukum, ada baiknya kita bercermin dari pengalaman Cina. Kekuatan atau nilai lebih pemberantasan korupsi yang dilakukan Cina adalah pada shock therapy atau rasa takut yang ditimbulkan, misalnya dengan adanya hukuman mati. Yang lebih penting lagi, hukuman benar-benar diterapkan secara nyata terhadap para pelaku korupsi yang sudah divonis pengadilan setempat. Buktinya, selama kurun waktu Januari sampai November 2004 yang lalu, pemerintah Cina telah sukses menangkap 4.225 koruptor dengan total kerugian negara 3,8 miliar yuan atau sekirar Rp 4,3 triliun.
Pemerintah Cina juga tidak pandang bulu, koruptor yang ditangkap pun terdiri dari berbagai lapisan pejabat, mulai dari level tertinggi sampai terendah. Laporan Kantor Berita Xinhua menyebutkan, pengadilan setempat tidak tanggung-tanggung dalam memvonis pelaku korupsi. Ada bekas gubernur yang telah divonis 11 tahun karena terbukti menerima suap sebesar 960.000 yuan atau sekitar Rp 1,1 miliar. Juga ada seorang mantan wali kota dieksekusi hukuman gantung, karena kasus korupsi senilai Rp 3,5 miliar. Selain menangkap 4.225 koruptor, juga ada 754 pegawai negeri di Cina yang dihukum karena menyalahgunakan uang negara.
Dalam hal korupsi, Cina benar-benar menerapkan hukuman tanpa pandang bulu. Sementara hukum di Indonesia ibarat sarang laba-laba: Ia hanya bisa menangkap nyamuk. Kalau burung besar yang lewat, maka koyaklah sarang laba-laba itu ... Tantangan itu kini menohok pada SBY. Beranikah ia mengambil pelajaran dari Cina, meniru langkah Zhu Rongji: memesan 100 peti mati, satu di antaranya untuk dirinya sendiri dan 99 lainnya diperuntukkan bagi pejabat yang terbukti korupsi.
3. Perbaikan aturan perundang-undangan
Banyak pihak menilai bahwa produk hukum mengenai tindak pidana korupsi sudah cukup memadai. Namun menurut pakar hukum Loebby Loqman, perbaikan dan penyempurnaan aturan perundang-undangan korupsi masih perlu terus dilakukan. Upaya ini setidaknya diorientasikan untuk mengantisipasi tumpang-tindihnya beberapa klausul tindak pidana korupsi dalam satu peraturan dengan peraturan lainnya. Selain itu juga perlu adanya kesamaan tafsir para penegak hukum terhadap klausul yang termuat dalam perundang-undangan.
Loebby memberi contoh, misalnya, tindak pidana korupsi sering dirumuskan sebagai delik materil. Akibatnya, jika sang koruptor mengembalikan uang yang dikorupsi, dianggap bahwa unsur kerugian negara sudah tidak ada lagi sehingga orang tersebut tidak lagi diajukan ke pengadilan. Sesungguhnya tindak pidana korupsi adalah tindak pidana formil. Jadi, perbuatan korupsinya yang dilarang, bukan akibatnya. Karena itu, meskipun uang yang dikorupsi itu dikembalikan ia harus tetap diajukan ke pengadilan. Adapun jika uang yang dikorupsi itu dikembalikan, hal itu dapat saja digunakan sebatas sebagai pertimbangan hakim untuk memperingan dalam penjatuhan pidana.
4. Pemberdayaan lembaga anti-korupsi
Meskipun awalnya sempat diwarnai sejumlah kontroversi, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mendapat apresiasi yang cukup positif dari masyarakat. Ini terutama terkait ‘keberhasilan’ KPK menangani praktik korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun begitu, tidak sedikit pula pihak yang mencibir KPK karena belum berhasil mengungkap skandal korupsi besar yang menjadi prioritas. Karena itu, di kalangan aktivis anti-korupsi tersiar istilah ‘tebang-pilih’ atas kinerja KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi.
Anggota Komisi II DPR Benny K. Harman menilai KPK masih gamang dalam mengungkap skandal korupsi. Kalau pun ada ‘keberhasilan’ itu masih bersifat artifisial. Peneliti korupsi, George Junus Aditjondro, bahkan menilai pengungkapan kasus korupsi di KPU itu sebagai upaya untuk “menyipilkan” korupsi seraya melupakan kasus-kasus korupsi sebelumnya yang banyak dilakukan oleh kalangan militer. Menurutnya, dengan membuat publik memberikan perhatian kepada korupsi di KPU, maka kesan yang timbul adalah orang-orang sipil telah melakukan korupsi yang luar biasa besarnya. “Ini merupakan salah satu kampanye hitam kepada masyarakat sipil”, ujarnya.
Di sisi lain, KPK tampak kurang bertenaga berhadapan dengan skandal korupsi besar. Padahal, KPK sejatinya memiliki kewenangan yang cukup besar, bahkan mungkin terlalu besar. Segala kewenangan koordinasi, supervisi, penyelidikan dan penuntutan serta pencegahan berada di tangan KPK. Menurut Romli Atmasasmita, dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, belum pernah ada lembaga yang memiliki kewenangan seluas KPK. Modal kewenangan yang besar ini sudah semestinya diperankan secara maksimal sehingga KPK benar-benar dapat menjadi tumpuan harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi..
5. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan korupsi
Pada kenyataanya, tindak korupsi terjadi dalam hubungan segi tiga antara negara, pengusaha dan masyarakat. Karena itu, Teten Masduki menilai kehadiran badan anti-korupsi yang dibentuk oleh negara sebenarnya belumlah cukup kalau tidak mendapat dukungan luas dari masyarakat. Salah satu keberhasilan Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hongkong karena dilengkapi “Komite Pengamatan” yang melibatkan warga masyarakat dan sektor swasta. Suatu perkara korupsi ditutup atau diteruskan ke pengadilan senantiasa atas sepengetahuan Komite, sehingga transparan. Karena itu, lembaga penyelidikan masyarakat (public enquiries) seperti ICW, Gerakan Masyarakat Peduli Harta Negara (Gempita), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), atau pers dan civil society lainnya, seharusnya mendapat tempat dalam sistem hukum kita agar peranannya bisa optimal dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan pemerintahan yang baik.
Sejalan dengan itu, penelitian Demos juga menyebutkan bahwa buruknya kinerja pemberantasan korupsi tak lepas dari lemahnya kontrol publik yang menjadi salah satu kunci demokrasi. Para informan penelitian Demos menilai bahwa kemampuan publik untuk melakukan kontrol tergolong rendah. Bukan hanya tak mampu, tapi akses untuk melakukan kontrol pun masih terbatas. Dalam konteks yang lebih besar, tidak terwakilinya kepentingan publik adalah masalah yang ada di balik itu semua. Proses demokratisasi selama lima tahun terakhir rupanya hanya melahirkan pola dan tingkah laku kekuasaan baru di kalangan elit lama, atau menciptakan aliansi baru di antara elit-elit politik lama dan baru. Kondisi inilah yang tampaknya membiarkan pintu bagi praktek korupsi tetap terbuka. Karena itu, pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan korupsi memiliki urgensinya tersendiri dalam upaya membasmi korupsi.
Akhirul Kalam
Meskipun banyak pihak menyangsikan keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia, Ketua MPR-RI, Hidayat Nur Wahid masih memiliki optimisme. Menurutnya, harapan yang kuat atas keberhasilan pemberantasan korupsi harus senantiasa dipelihara atau bahkan diciptakan. Untuk itu ada syaratnya yang tidak bisa ditawar, yaitu tekad dan kebersamaan pemerintah dengan masyarakat. Keberhasilan pemberantasan korupsi di Hongkong merupakan salah satu contoh bahwa tekad yang kuat dan kebersamaan pemerintah dengan rakyat mampu mengubah kondisi yang tak berpengharapan menjadi sebuah keberhasilan yang fenomenal.
Harapan yang diungkapkan Hidayat agaknya tidak berlebihan. Pesan moralnya sama dan sebangun dengan ‘kampanye’ yang sering dilontarkan ketua Transparency International, Peter Eigen: “Tidak ada satu pihak pun yang mampu memberantas korupsi sendirian!”. Menurutnya, perang terhadap korupsi harus dilakukan bersama oleh pemerintah, sektor swasta, civil society, termasuk rakyat dari semua lapisan. Persoalannya kemudian adalah mampukah gerakan pemberantasan korupsi menjadi kesadaran kolektif yang menyinergikan segenap potensi bangsa ini secara massif? Dengan begitu, harapan kita untuk mewujudkan Indonesia tanpa korupsi benar-benar menjadi kenyataan.
***
Holloway, Nono Anwar Makarim (eds.), Mencuri Uang Rakyat: Buku 2, Aksara, Jakarta.
Lebih rinci dapat disimak dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasannya.
Raharjo, M. Dawam (1999), “Korupsi, Kolusi dan Nepoteisme (KKN): Kajian Konseptual dan Kultural”, dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (ed), Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepoteisme di Indonesia, Aditya Media, Yogyakarta.
Wammey, J.M. (1999), “Can Corruption be Measured? Bank Offers Diagnostic Tools to Measure and Combat Corruption in Member Countries.” Bank's World, Vol.3 No.6, Website: http\\www.ext/worldbank.org/bw7.
Sairin, Sjafri, “Efektivitas Gerakan Kultural Dalam Pemberantasan Korupsi nasional,” dalam makalah untuk Seminar Nasional Gerakan Kultural Anti Korupsi dan Pemilihan Ekonomi dalam Rangka Sosialisasi Etika Kehidupan Berbangsa, diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Sejarah dan Purbakala Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata RI dan Pengurus Pusat Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, Jakarta: 21 Juli 2004.
Kompas, “Demoralisasi Niat Memicu Maraknya Korupsi”, 6 Februari 2003.
Subagija, Stevanus, “Korupsi yang Sebenar-benarnya”, dalam Pikiran Rakyat, Bandung: 8 April 2004.
Ulasan paling relevan dapat disimak dalam Muhammad Qodari, “KKN: Musuh yang Tak Tertaklukkan”, dalam Stanley (2005), Warisan Orde Baru: Studi Fenomena dan Sistem Bablasan Rezim Soeharto di Era Reformasi, Institut Studi Arus Informasi, Jakarta.
Saragih, Simon, “Korupsi itu Sangat Keji,” dalam Kompas, 19 Januari 2000.
Gie, Kwik Kian (2003), Pemberantasan Korupsi untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan, Jakarta: Tanpa Penerbit.
Bhargava, Vinay and Emil Bolengaita (2004), Challenging Corruption in Asia: Case Studies and Framework for Action, The World Bank, Washington, DC.
Pope, Jeremy (2003), Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem integritas Nasional, Yayasan Obor Indonesia dan Transparency International Indonesia, Jakarta.
Teten Masduki, “Badan Anti Korupsi”, dalam Tempo Interaktif, 8 Juli 2004.
Samadhi, Willy Purna, “Demokrasi Kita Dimakan Benalu”, dalam Majalah Tempo, 5 Juni 2005.