
Membayangkan Model Ideal Hubungan Industrial
Perspektif Serikat Pekerja
Sofian Muawar Asgart
Pendahuluan
Dunia perburuhan atau ketenagakerjaan pada umumnya mengalami perubahan cukup signifikan seiring terjadinya perubahan politik dan ekonomi global. Terutama dengan adanya perubahan di bidang ketenagakerjaan yang didorong oleh kesepakatan negara-negara anggota organisasi buruh internasional (International Labour Organization/ ILO) untuk menerapkan konvensi-konvensi dasar yang disepakatinya. Dalam konteks Indonesia, perubahan ketenagakerjaan memang relatif lambat. Ini disebabkan terutama akibat mental dan pola pikir yang belum siap dari para elit yang ada, baik dari kalangan birokrasi atau para pejabat yang berkompeten, pengusaha, maupun elit serikat pekerja yang menunjukkan ketidaksiapan untuk ikut dalam perubahan itu. Kondisi ini antara lain dapat dilihat dari banyaknya kasus konflik ketenagakerjaan yang tidak dapat diselesaikan secara elegan oleh ketiga pihak. Padahal, setiap aktivitas ketenagakerjaan baik kecil maupun besar selalu menyangkut kepentingan banyak pihak, yakni kepentingan pengusaha, pekerja, pemerintah, serta kepentingan masyarakat pada umumnya.
Ironisnya, dalam waktu yang lama telah terjadi persepsi yang keliru. Banyak pihak menilai bahwa urusan ketenagakerjaan hanyalah kepentingan pengusaha dan para pemilik modal saja. Padahal, kenyataannya, soal ketenagakerjaan adalah merupakan kepentingan bersama. Bahkan, masyarakat secara umum pun terbukti mempunyai kepentingan atas baiknya kinerja perusahaan dalam hal menyediakan produk dan jasa, menciptakan kesempatan kerja, dan menyerap pencari kerja. Pemerintah sendiri berkepentingan agar masyakarakat dapat memperoleh kesejahteraaan dengan luasnya kesempatan bekerja. Kesadaran inilah yang mengharuskan hubungan industrial menjadi bagian dari public matters yang perlu diperhatikan semua pihak dan tidak diartikan secara sempit sebatas hubungan kerja semata.
Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku ekonomi dalam proses produksi barang atau jasa, yang terdiri dari pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Sedangkan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja tertentu yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dari uraian itu, jelas bahwa hubungan industrial yang terbentuk antara pelaku proses produksi mempunyai pengertian lebih luas. Bahkan, hubungan industrial memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam konstelasi perekonomian nasional. Karena itu, sebagai bagian integral dari tiga pilar ekonomi nasional, kelompok pekerja perlu memahami fungsi, peran, dan kapasitasnya secara memadai.
Hubungan industrial, dari mana mau kemana?
Pada hakikatnya, hubungan industrial adalah interaksi sosial antarmanusia dalam proses produksi barang dan jasa untuk pemenuhan masyarakat. Mekanisme hubungan industrial antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah (tripartrit) telah diatur dalam beragam ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, prinsip dasar yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan meliputi pengerahan dan penempatan tenaga kerja, kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja asing, pembinaan hubungan industrial, pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja, pengawasan tenaga kerja, dan ratifikasi Konvensi ILO.
Menurut Goenawan Oetomo (2006) dari semua ketentuan itu, secara teoretis peraturan dan perundang-undangan perburuhan di Indonesia sebenarnya telah memadai oleh karena hampir semua aspek penting bidang perburuhan telah diatur. Namun, hal lain yang sangat mempengaruhi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah datang dari ketiga pihak: kebijakan pemerintah, kejujuran, dan ketaatan pengusaha, serta kejujuran dan ketaatan para pekerja. Ketiga faktor inilah yang akan menentukan apakah penerapan hukum perburuhan itu dapat dilaksanakan atau justru akan dikecualikan dan dilanggar. Dari pengalaman selama 30 tahun, semua pihak tahu kalau pemerintah kurang memberi kesempatan kepada semua pihak untuk bergerak sesuai dengan hati nuraninya. Hal ini dilakukan sekadar untuk meredam gejolak yang akan mengganggu jalannya stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan.
Ironisnya, dasar awal yang berprinsip baik tadi semakin lama menjadi semakin kabur karena pada akhirnya dalam realitas menjelma menjadi kekuatan yang menekan demokrasi, kebebasan, dan keharmonisan masyarakat. Upaya yang ditancapkan dalam prinsip hubungan industrial Pancasila hanya slogan belaka. Rumusan yang baik pada akhirnya menjadi sangat tidak bermanfaat karena tidak dapat ditemui dalam realitas. Istilah "pengusaha adalah mitra buruh" dan "buruh adalah mitra pengusaha" hanyalah samar-samar ditemui dalam pelaksanaannya. Sistem satu organisasi buruh dan satu organisasi pengusaha ternyata mendatangkan kenyataan monopoli wewenang di segala bidang perburuhan yang mengakibatkan suara yang berbeda disingkirkan. Situasi ini menimbulkan tekanan terhadap kaum buruh maupun terhadap pengusaha, baik individual maupun kolektif dalam organisasinya.
Dalam kondisi semacam ini masing-masing pihak baik pengusaha, buruh, maupun pemerintah merupakan pihak yang saling berlawanan dan bermusuhan. Usaha yang semula hendak berlandaskan maksud dan tujuan baik dari semua pihak, seperti upaya menghasilkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan justru menimbulkan reaksi yang keras dari kalangan organisasi buruh oleh karena latar belakang yang mengawali lahirnya undang-undang tersebut dinilai melanggar hukum. Hal ini mengakibatkan penundaan berlakunya undang-undang tersebut, meski telah menghabiskan biaya yang sangat besar. Padahal, hubungan industrial, idealnya harus merupakan proses terbinanya komunikasi, konsultasi, musyawarah, serta dialog yang ditopang oleh kemampuan dan komitmen yang tinggi dari semua unsur tripatrit.
Kondisi serikat pekerja
Wacana mengenai hubungan industrial sejatinya telah lama diperbincangkan, namun perkembangannya, sepertinya hanya jalan di tempat. Karenanya, banyak pihak, terutama kalangan serikat pekerja seringkali merasa ”alergi” membincangkannya. Tidak sedikit kelompok serikat pekerja yang merasa pesimis atas kondisi hubungan industrial yang berlangsung selama ini. ”Pengusaha dan penguasa seringkali bersekongkol untuk memeras dan merampas hak-hak pekerja,” ucap Koordinator KASBI, Anwar Sastro Makruf. Padahal menurutnya, hakikat hubungan industrial harus mengacu pada tujuan pembangunan, yakni memberdayakan ekonomi nasional. Karena itu, buruh atau pekerja perlu memperoleh perlindungan dalam semua aspek oleh karena dibanding pengusaha, posisi pekerja paling lemah, terutama dalam aspek ekonomi.
Dari perspektif pekerja, kegiatan hubungan industrial idealnya mampu mendorong para pekerja agar mendapat manfaat untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hubungan industrial juga harus mendorong terjadinya proses pembelajaran pekerja sehingga terjadi pengembangan wawasan dan peningkatan keterampilan kerja yang dapat memperbaiki kualitas hidupnya. Hubungan industrial juga harus berdampak pada perlindungan hak dasar pekerja, pemenuhan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, yang meliputi rasa aman sebagai kebutuhan dasar dan terpenuhinnya kebutuhan sosial minimum pekerja dalam hubungan industrial yang harmonis serta terpenuhinya kebutuhan pengembangan diri pekerja sebagai penyaluran aspirasi.
Namun ironisnya, kondisi internal serikat pekerja juga tak luput dari masalah. Selain harus berhadapan dengan konflik eksternal dalam konteks hubungan industrial dan tripartit, serikat pekerja juga seringkali dilanda konflik internal yang cukup pelik. Fragmentasi organisasi serikat pekerja sudah bukan rahasia lagi. Karenanya, alih-alih ingin membangun bargaining position dalam kerangka hubungan industrial, organisasi serikat pekerja juga dihadang pekerjaan rumah yang sulit di internal organisasinya. Kondisi ini tentu cukup menguras energi serikat pekerja, sekaligus memperburuk citra serikat pekerja di mata publik dengan tampilnya kesan sebagai organisasi yang fragmented, egois, dan parsial.
Hasil riset DEMOS (2005) menunjukkan bahwa dari beragam isu dan kepentingan yang diusung serikat pekerja, hanya sedikit agenda dan visi yang komprehensif. Sementara kapasitas para aktivis buruh dalam menghadapi problem-problem pemerintahan dan khususnya keterwakilan berkaitan erat dengan karakter isu-isu dan perspektif-perspektif kelompok-kelompok informan tersebut bekerja, masih tetap dominan. Ini menunjukkan kecenderungan umum, adanya dominasi kebijakan gerakan yang bertumpukan pada karakter issu dan kepentingan spesifik, yakni sebesar 46 persen. Sementara issu dan kepentingan umum sebesar 33 persen, sedang gagasan atau nilai-nilai umum hanya 31 persen. Artinya, aktivisme yang dilakukan kelompok pekerja masih terjebak partikularitas yang parsial.
Sementara itu, laporan penelitian AKATIGA-TURC-Lab Sosio UI (2005) bahkan menyebutkan bahwa perjuangan serikat pekerja di Indonesia telah mengalami pergeseran dari perjuangan untuk kesejahteraan ke perjuangan eksistensial sekadar mempertahankan pekerjaan itu sendiri. Contoh nyata misalnya ketika para aktivis pro-demokrasi melakukan demontrasi menolak Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (UU APP). Pada momen itu, tampaknya kalangan serikat pekerja tidak cukup tersentuh. Padahal, secara langsung maupun tidak langsung hal ini juga memiliki keterkaitan dengan kepentingan para buruh juga, terutama hak-hak buruh perempuan.
Kondisi ini ternyata juga disadari oleh kelompok serikat buruh. Aktivis Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Dita Indah Sari mengungkapkan bahwa gerakan buruh saat ini kondisinya sangat fragmented, terfragmentasi secara sangat dalam, secara sangat luas. Fragmentasi itu bisa berdasarkan orientasi dan afiliasi politiknya, programnya, figurnya, dan macam-macam. Problem ini menurutnya yang menjadi masalah utama buruh sehingga tidak memiliki posisi tawar-politis yang kuat, baik dengan pengusaha maupun dengan penguasa. Problem kedua adalah rendahnya kesadaran berorganisasi di kalangan buruh dan ini terkait dengan warisan depolitisasi Orde Baru yang cukup lama. Pada saat itu hampir semua sektor di-depolitisasi, termasuk sektor buruh sehingga para buruh cenderung menghindari persoalan-persoalan politik konkret. Kondisi ini akhirnya menjebak aktivis buruh untuk terlibat hanya pada persoalan-persoalan spesifik buruh semata. Mereka hanya sibuk dengan urusan-urusan sektornya saja dan jarang terlibat dalam persoalan-persoalan kebangsaan yang lebih luas. “Dua hal inilah soal fragmentasi dan rendahnya kesadaran yang menjadi problem utama yang mengakibatkan gerakan buruh belum menjadi kekuatan yang signifikan sebagai kekuatan politik,” ujar Dita Sari.
Mempromosikan pakta sosial
Gagasan mengenai pakta sosial (social pact) sejatinya bukanlah sesuatu yang asing dalam konteks sosial-politik di Indonesia. Menurut Olle Tornquist (2006), upaya ini setidaknya dapat dirujuk pada pengalaman politik dari tahun 1945 hingga 1948 dimana telah terjadi kesepakatan yang luas diantara sejumlah kelas dan kelompok yang modern, plural, dan berdasarkan atas hak, demokrasi, dan berdasar pada konsep negara-bangsa yang independen. Hal yang sama juga pernah terjadi antara tahun 1952 dan 1965 dimana ”kaum borjuis nasional” (national bourgeoisie), membangun kesepakatan bersama diantara para kelompok buruh dan kaum tani.
Pakta sosial secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah hasil yang didapat dari proses dialog pada level nasional mengenai issu-issu bersama yang berkaitan dengan masalah kebijakan sosial dan ekonomi diantara pihak pengusaha, pekerja (buruh), dan pemerintah. Pada tataran praksisnya, pakta sosial ini dapat mewujud dalam beragam aktivitas, seperti negoisasi dan pengambilan keputusan bersama (concertation). Pada akhirnya pakta sosial ini diharapkan menghasilkan konsesus, setelah pihak-pihak yang terlibat melakukan terobosan dan mendamaikan kepentingan-kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan titik temu yang dapat disepakati bersama. Jika mengacu pada pengalaman di beberapa negara, pada dasarnya semua model pakta sosial yang ada secara fundamental berbasis pada kepentingan ekonomi bersama dari aspek yang sangat penting dan strategis, baik dari sudut modal atau pengusaha maupun dari sudut organisasi buruh.
Apakah pengalaman itu dapat dieksplorasi kemungkinannya untuk diterapkan dan dikontekstualisasikan di Indonesia ? Dalam konteks ini, Olle Tornquist mengajukan dua pertanyaan utama. Pertama, apa pilar-pilar yang dipromosikan dan bagaimana dinamika yang terjadi, serta masalah-masalah apa yang dihadapi oleh pakta-pakta sosial yang ada? Kedua, bagaimana itu semua di-’de-contextualised’ sehingga kita dapat mengidentifikasi berbagai pra-kondisi dan faktor-faktor ’minimum’ yang umum, dan untuk kemudian dieksplorasi kemungkinannya bila ini dikembangkan dalam konteks Indonesia.
Goverment
Corporate Sector Society
Dalam kerangka seperti itu, maka buruh tidak bisa diberi beban yang lebih berat untuk bertarung vis a vis dengan dunia usaha. Namun tugas ini harus dipikul secara bersama oleh society at large dimana buruh sendiri hanya salah satu bagiannya. Menurutnya, semua permasalahan tersebut tidak bisa semerta-merta dibebankan kepada kelompok atau serikat buruh semata. Justru kelompok buruh-lah yang harus mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk para ekonom, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya, terutama media.
Yanuar mencontohkan, misalnya, dalam hal tuntutan peningkatan upah. Ketika buruh meminta upahnya ditingkatkan, seharusnya pihak-pihak lain turut mendukung, dan bukannya melihatnya sebagai keegoisan sikap buruh. Mengapa ini perlu ditempuh? Karena kalau buruh medapatkan kenaikan gaji, maka perputaran uang itu juga akan kembali ke masyarakat. “Bukan hanya buruh yang diuntungkan, tapi juga kelompok masyarakat lain seperti tukang bubur atau tukang bakso di sekitar pabrik, pemilik kontrakan rumah, jasa transportasi, dan kelompok masyarakat lainnya. Demikian juga ketika terjadi PHK massal, semua juga terkena dampaknya. Jadi, ekonomi itu harus dilihat sebagai bagian dari solidaritas. Sistem ekonomi hanya dapat berjalan apabila ada solidaritas diantara semua kelompok masyarakat,” ujarnya.
Dalam konteks pakta sosial, kelompok pengusaha juga harus “meluruskan” pola pikirnya bahwa dia bukan saja membuat job market, tapi juga membutuhkan market region. Karena itu, pengusaha tidak hanya melihat buruh sebagai pekerja semata, tapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang menjadi target market (pembeli) dari produknya. Karena itu, ketika pengusaha menaikkan upah buruh, sejatinya ia sedang meningkatkan daya beli masyarakat agar masyarakat sanggup membeli barang dagangannya. “Jadi itulah yang namanya transaksi negara yang sekaligus juga transaksi social multiflier effect dimana sesungguhnya kenaikan upah buruh juga akan berimplikasi terhadap dunia usaha secara timbal balik,” tambah Yanuar. Dalam kerangka inilah pakta sosial menjadi hal yang penting untuk dibangun secara bersama antara pemerintah, corporate sector, dan buruh sebagai bagian tak terpisahkan dari society.
Menurut Rekson Silaban, salah satu kegagalan tidak mulusnya hubungan industrial di Indonesia adalah karena rendahnya rasa saling percaya antara buruh dengan pengusaha. Buruh selalu melihat pengusaha adalah pembohong yang selalu mendeklarasikan kerugian sementara pengusaha memandang serikat buruh sebagai lembaga yang tahunya hanya menuntut tanpa peduli dengan kesulitan pengusaha. Selain itu, hukum perburuhan di Indonesia tidak mengharuskan kedua belah pihak –buruh dan majikan– bersedia melakukan perundingan bila ada masalah. UU perburuhan hanya menulis mekanisme perundingan bila kedua belah pihak mau berunding, tapi tidak mengharuskan pihak-pihak untuk berunding. Jadi bila ada masalah hubungan industrial, tidak ada kewajiban bagi kedua belah pihak untuk berunding. “Pengusaha bisa menghindari perundingan dengan berdalih sedang sibuk, begitu pula sebaliknya. Inilah kasus yang selama ini membuat hubungan industrial kita buruk dan menjadi pemicu utama maraknya pemogokan,” ujarnya.
Karena itu, menurut Rekson, kunci utama bagi pembentukan pakta sosial adalah diupayakannya social dialogue (dialog sosial). “Pakta sosial harus dimulai dari dialog sosial, karena tidak mungkin ada pakta sosial tanpa didahului dengan dialog sosial,” tambahnya. Namun justru budaya dialog inilah yang minim dimiliki serikat buruh maupun pengusaha dalam konteks hubungan industrial. Bagi kalangan buruh sendiri miskinnya budaya dialog ini mungkin sebagai akibat pengalaman buruk masa lalu, dimana pemerintah dan pengusaha seringkali berkolaborasi merepresi buruh sehingga banyak aktivis serikat buruh yang tidak mempercayai pengusaha maupun pemerintah. Akibatnya, buruh dan serikat buruh dalam beberapa peristiwa lebih menghendaki penyelesaian masalah melalui penekanan massa (presser group), seperti unjuk rasa dan mogok kerja ketimbang melalui jalur dialog. Namun tanpa disadari, pola perjuangan seperti ini menciptakan semacam “api dalam sekam” karena pengusaha yang dipaksa menyetujui sesuatu melalui desakan massa hanya menunggu momentum lain untuk melakukan pembalasan (lock out). Contoh nyata atas kasus ini, misalnya, hengkangnya perusahaan Sony ke Malaysia pada tahun 2004. Sony memilih Malaysia sebagai tempat beroperasi sekalipun upah buruh di sana 2/3 kali lebih mahal dari Indonesia.
Kendala lain yang menghambat dibangunnya pakta sosial adalah lemahnya peran pemerintah. Aktivis SBTPI, Dedi Fauzi, menilai pemerintah tidak mampu menjembatani kepentingan buruh dan pengusaha. Dalam banyak kasus, bahkan, pemerintah cenderung membela kepentingan pengusaha dari pada kepentingan buruh. Sementara itu, semangat pengusaha untuk membangun pakta sosial pun patut dicurigai karena beberapa pengalaman menunjukkan bahwa mereka hanya memanfaatkan momentum semata. ”Dulu kami pernah demontrasi bersama pengusaha untuk menekan pemerintah agar membatalkan kenaikan BBM. Namun ternyata para pengusaha itu hanya memanfaatkan kita saja,” ujarnya.
Berbagai kendala itulah yang menjadi alasan beberapa aktivis serikat buruh menyampaikan pesimismenya bagi upaya pembentukan pakta sosial. Aktivis gerakan anti-korupsi yang pernah malang-melintang di dunia perburuhan, Teten Masduki, juga merasa pesimis atas upaya pembentukan pakta sosial itu. Namun menurutnya bukan berarti hal itu tidak mungkin. Hanya saja dibutuhkan beberapa prasyarat dan pra-kondisi agar alternatif itu menjadi masuk akal. Prasyarat dan prakondisi itu terutama adanya organisasi buruh yang solid, ”kedewasaan” para pengusaha, serta goodwill dan political will dari pemerintah atas persoalan-persoalan ketenagakerjaan dan kesejahteraan.
Sejalan dengan itu, aktivis SPN, Lilis Mammudah, menyatakan bahwa meskipun sangat sulit membayangkannya, namun upaya pembentukan pakta sosial bukanlah sesuatu yang mustahil sejauh kita mampu menyiapkan berbagai pra-kondisi sebagai prasyaratnya. ”Itu saya kira masih mungkin, bahkan, pakta sosial ke depan sangat penting untuk terus diupayakan. Tapi ini pun bukan hanya sebatas basa-basi pula. Artinya semua pilar harus merasa penting untuk membangunnya,” ujarnya. Dari perspektif kelompok buruh, Lilis menawarkan pra-kondisi sebagai syaratnya, terutama organisasi buruh sendiri harus melakukan evaluasi dan introspeksi atas gerakannya selama ini. Jangan-jangan posisinya yang underdog ini disebabkan karena kapabelitas dan SDM buruh memang rendah sehingga sangat mudah dibodohi dan dibohongi. Untuk itu menjadi penting bagi para aktivis buruh melakukan up-grading kemampuannya sehingga ia akan memiliki posisi tawar yang baik.
Sejalan dengan itu, Dita Indah Sari juga berkomentar bahwa kondisi perburuhan kita saat ini memang sulit dan sangat memprihatinkan, tapi bukan berarti tertutup kemungkinan bagi upaya pembangunan fakta sosial. Ia masih optimis bahwa upaya pembentukan pakta sosial di Indonesia masih sangat memungkinkan. Untuk itu, perlu upaya-upaya keras dari sejumlah tokoh buruh untuk meyakinkan unsur-unsur lain tentang apa yang akan di-pakta-kan. Persoalan yang menjadi konsensus untuk di-pakta-kan juga tidak terbatas pada kepentingan buruh dan pengusaha semata, tapi pada kepentingan yang lebih besar, misalnya dalam rangka melindungi industri nasional secara bersama-sama. “Kalau kepentingan yang lebih luas itu yang menjadi basisnya, saya kira sangat bisa. Karena faktanya sekarang industri dalam negeri sedang terdesak, para pengusaha juga banyak yang bangkrut dan tidak punya perlindungan yang memadai sementara kapasitas produksinya rendah. Dalam kondisi seperti ini saya kira semua pihak bisa duduk bersama dan berpikir bersama secara jernih,” ujarnya.
Dengan berbagai argumen tersebut sejatinya pakta sosial masih sangat mungkin diupayakan di Indonesia. Hanya saja upaya ini jangan diorientasikan pada hal-hal yang spesifik seperti batasan upah, meskipun itu juga penting. Hal-hal seperti itu cukuplah diurus oleh serikat-serikat buruh sektor di tingkat pabrik, sementara dalam pakta sosial lebih berorientasi pada kepentingan yang lebih luas dan longterm sehingga dapat mengikat secara lebih umum dan secara nasional. Jika itu yang diupayakan, besar kemungkinan pakta sosial akan mendapat dukungan luas dari banyak pihak, karena mereka sama-sama diuntungkan.
Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah keseriusan dari semua pihak untuk terus melakukan eksprimentasi termasuk juga dengan melakukan komparasi dengan pengalaman-pengalaman di beberapa negara yang telah terbukti sukses mempraktekkan model pakta sosial. Sebagai bahan bandingan, misalnya, pengalaman beberapa negara Eropa, terutama negara-negara Skandinavia yang telah berhasil membangun pakta sosial melalui pengaturan perundingan yang didasarkan atas niat baik para pihak untuk mengedepankan perundingan yang tulus (good faith negotiation). Model ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pakta sosial di Indonesia. Kuncinya tentu saja dengan mencoba untuk terus bereksperimentasi secara bertahap dan ditempuh secara bersama-sama. Model ini tentu mensyaratkan kesiapan semua pihak untuk membuka diri dan kesediaan semua pihak untuk berdialog secara tulus dalam rangka meraih solusi terbaik untuk kepentingan bersama.
***

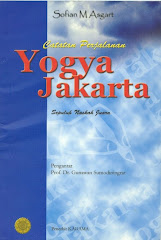



Tidak ada komentar:
Posting Komentar