
Hirup pikuk pemilu 2009 telah begitu banyak menyita perhatian berbagai kalangan. Tak terkecuali kelompok perempuan yang sejatinya merupakan segmen-konstituen politik terbesar. Karena itu, isu ’politik perempuan’ dalam pemilu terdengar kian santer. Entah karena niatan tulus para politisi untuk mengakomodasi dan mengagregasi suara dan kepentingan perempuan atau sekadar berebut memanfaatkan tambang suara yang menggiurkan itu.
Untuk mengkritisi wacana ’politik perempuan’ terutama dalam konteks pemilu, Demos telah melakukan serangkaian diskusi terfokus (focus group discussion). Agenda ini, terutama difokuskan untuk mengevaluasi dan mencari solusi sekaligus mempromosikan alternatif, baik secara normatif maupun praktis, demokrasi yang lebih ramah gender (gender democracy). Selain itu, proyeksinya juga diorientasikan dalam rangka mempromosikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk gerakan peremuan –atau kalangan yang secara umum concern dengan isu kesetaraan dan keadilan gender– dalam konteks politik dan demokrasi.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22-24/PUU-VI/2008 sungguh telah menjadi polemik baru, terutama di kalangan para calon legislator (Caleg) degan beragam kepentingannya. Sebagian kalangan menilai bahwa putusan itu akan memperbaiki kualitas Pemilu 2009 karena jelas memperkuat legitimasi politik dengan terpilihnya calon berdasarkan jumlah suara terbanyak secara mutlak. Namun begitu, tidak sedikit pula yang melihat bahwa putusan itu merupakan kendala baru yang menghambat. Banyak kalangan aktivis perempuan, bahkan menganggap pengaturan quota 30 persen bagi caleg perempuan dalam UU No.10/2008, dengan sistem setiap tiga caleg salah satunya adalah perempuan menjadi tidak lagi berarti dan berpengaruh.
Konsekuensinya, berbagai kelompok aktivis perempuan menolak putusan tersebut karena dianggap tidak pro-perempuan yang selama ini merasa menjadi kelompok subordinasi laki-laki. Di kalangan anggota MK sendiri, bahkan, salah seorang anggotanya, Maria Farida Indrati, mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion). Menurutnya, quota perempuan perlu diperjuangkan sebagai suatu hak konstitusional. Sebagian kelompok aktivis perempuan menggangap bahwa selama posisi pengambilan keputusan politik, kerja, pendapatan dan waktu tidak pernah bisa didistribusikan secara setara (unequally distributed) antara laki-laki dan perempuan, maka bisa dikatakan bahwa masih ada defisit demokrasi (democratic deficit) pada negara dan masyarakat di Indonesia. Ini artinya, demokrasi kita masih belum lengkap (still incomplete).
Peneliti Demos, Nur Iman Subono menyebutkan bahwa upaya gerakan perempuan di Indonesia selama ini, dengan segala kelemahannya baik karena berbagai isu yang ada, model gerakan yang dipilih, dan fragmentasi yang tampil, memiliki tujuan untuk mempromosikan demokrasi yang berkeadilan. Karenanya, kebijakan afirmatif, kuota 30% dalam sistem pemilu dan kepartaian yang lebih ramah perempuan dan lainnya adalah instrumen politik yang digunakan untuk memcapai tujuan tersebut. ”Gampangnya, merujuk pada Claudia Neusuess, Heinrich Boell Foundation, perjuangan tersebut sebagai upaya untuk mewujdkan apa yang disebut sebagai demokrasi gender (gender democracy) sebagai altenatif atau koreksi atas demokrasi perwakilan (demokrasi liberal),” ujarnya.
Dalam kasus Indonesia, seluruh upaya tersebut menjadi mentah kembali atau kembali ke titik nol, pada saat MK mengeluarkan keputusan yang pada intinya mempromosikan bahwa penentuan calon terpilih dengan suara terbanyak dianggap lebih mencerminikan kedaulatan rakyat, dan lebih sejalan dengan UUD 1945. ”Ini artinya, cara-cara di dalam demokrasi di luar suara terbanyak diartikan sebagai bertentangan dengan kedaulatan rakyat dan UUD 1945,” tambahnya. Senada dengan ini, Direktur PUSKAPOL UI, Sri Budi Eko Wardani menilai bahwa keputusan MK yang membatalkan pasal 214 UU No.10/2008 membuat keterwakilan perempuan di parlemen menjadi sulit diprediksi. Dengan mengacu pada situasi yang berkembang, Eko Wardani menilai bahwa jumlah politisi perempuan yang akan masuk senayan akan berkurang. Dalam konteks inilah suara terbanyak itu menjadi tidak sejalan dengan prinsip keadilan. ”Bagaimana mungkin masyarakat yang terdiri dari perempuan dan laki-laki dalam jumlah berimbang, ternyata tidak memiliki perwakilan yang seimbang,” ujarnya.
Kelompok Buruh Perempuan
Meskipun banyak kelompok perempuan yang tidak sepakat dengan hadirnya Putusan MK karena dianggap merugikan Caleg perempuan, namun tidak sedikit pula aktivis yang tidak begitu mempermasalahkannya. Aktivis TURC, Rita Olivia Tambunan, misalnya, menilai bahwa putusan MK itu tidak selayaknya direspon secara sempit hanya karena alasan adanya kelompok perempuan tertentu yang dirugikan. Menurutnya, putusan MK itu harus direspon dengan melihat konteks kepentingan politik demokrasi yang lebih luas, meskipun juga harus tetap melihat kepentingan sektoral tertentu, seperti buruh, petani, miskin kota, dan sektor lainnya yang seringkali terpinggirkan proses politik elektoral.
Rita, bahkan, melihat ’perempuan’ itu bukan sektor, tapi hanya issu. Karena itu, di kalangan buruh, termasuk juga para buruh perempuan lebih ’nyaring’ disuarakan kampanye ”buruh pilih buruh” ketimbang seperti kampanyenya kelompok aktivis perempuan yang punya slogan ”perempuan pilih perempuan”. Peneliti Perburuhan Endang Rokhani, menilai bahwa dengan slogan ”buruh pilih buruh” itu bukan berarti kelompok buruh perempuan secara dikotomis tidak mendukung kampanye ”perempuan pilih perempuan” namun memang ada skala prioritas tersendiri di kalangan buruh untuk menggolkan kepentingan mereka melalui Caleg dari kelompok buruh tanpa melihat apakah itu laki-laki atau perempuan. Bahkan, mungkin juga tanpa melihat dari partai mana pun. ”Apapun partainya, yang penting punya kepedulian terhadap isu-isu dan kepentingan buruh,” ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Divisi Perempuan DPP FSPMI, Aghni Dhamayanti. Menurut Aghni, saat ini ada banyak aktivis buruh yang menjadi Caleg dari berbagai partai. Ini merupakan salah satu upaya kelompok buruh untuk membawa aspirasi mereka melalui mekanisme politik elektoral. Aghni menilai bahwa upaya ini merupakan suatu keniscayaan karena kelompok buruh merupakan konstituen politik yang cukup signifikan. “Jumlah buruh berdasarkan data BPS Februari 2008 adalah 102.049.857 dengan perincian buruh perempuan 38.690210 (38%), dan buruh laki-laki 63.359.647 (62%). Dalam konteks pemilu, jumlah buruh perempuan di Indonesia adalah sekitar 42% dari jumlah pemilih,” ujarnya.
Menuju Representasi yang lebih Bermakna!
Harus diakui bahwa representasi politik perempuan merupakan elemen utama dalam demokrasi yang ramah gender (gender democracy). Menurut Nur Iman Subono tidak ada demokrasi yang sejati tanpa melibatkan representasi perempuan di dalamnya. ”Sangat berbeda dengan politisi laki-laki yang selalu asyik dengan “narasi-narasi besar politik”, kalangan aktivis perempuan tampaknya lebih fokus dan konsisten dalam pilihan politiknya yakni perjuangan kuota 30% untuk representasi politik perempuan,” ujarnya. Kelompok perempuan tidak terlalu terpengaruh hiruk pikuknya “politik” yang memang sangat kentara warna maskulinnya. Bagi kelompok perempuan, parlemen dan partai politik dalam sistem demokrasi, selain sistem pemilu, adalah tempat representasi politik perempuan dipertaruhkan. Karenanya, tidak mengherankan juga seluruh energi aktivis perempuan, baik dari kalangan politisi, aktivis LSM dan ormas, akademisi, maupun jurnalis perempuan, mencurahkan perhatian untuk mengupayakan representasi politik perempuan yang lebih adil dengan mengedepankan prinsip kesetaraan.
Namun meskipun memang sangat strategis, ternyata perjuangan kuota 30% hanyalah salah satu elemen utama dalam upaya mempromosikan representasi politik perempuan. Sudah saatnya, kalangan perempuan memperluas makna representasi politiknya. Keterlibatan perempuan dalam sistem politik untuk tujuan representasi memang diperlukan, tapi sudah pasti tidak cukup memadai. Karenanya ini harus diimbangi dengan tindakan-tindakan politik dalam kelompok-kelompok dan gerakan perempuan (Lister, 1997). Ini artinya, upaya go politics dari kalangan perempuan tidak hanya sebagai kegiatan untuk memasuki proses, mekanisme, lembaga, dan sistem politik (crafting democracy) secara prosedural semata, tapi juga bagaimana memperluas basis konstituen (broadening base) untuk kepentingan representasi politik yang lebih luas.
Setidaknya, ada dua dimensi utama di sini yakni, (1) menyangkut upaya untuk mempengaruhi proses-proses pengambilan keputusan publik; dan (2) usaha untuk membangun basis sosial representasi politik perempuan baik melalui lembaga-lembaga representasi politik, baik formal maupun informal, serta partisipasi langsung (direct democracy). Sejalan dengan itu, perlu juga dibangun rekoneksi antara gerakan perempuan, yang menjadi bagian dari gerakan sosial, dengan aksi-aksi politik, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari representasi demokrasi.
Menurut Lovenduski, kelompok perempuan pada dasarnya merepresentasikan tiga elemen (triple representatives), yakni mewakili pemilihnya (functional), partai dan organisasi politiknya (ideologi) dan konstituen perempuan sebagai identitas (social). Bagaimana mensinergikan ketiganya dalam rekoneksitas tindakan-tindakan politik dengan gerakan sosial perempuan? Ini merupakan tantangan yang harus dijawab kalangan aktivis perempuan. Karena itu di masa-masa mendatang, khususnya menjelang pemilu 2009 dan sesudahnya, kalangan aktivis dan politisi perempuan sudah harus melangkah lebih jauh lagi (byon election) dengan mempromosikan representasi politik demokratik yang lebih bermakna.// sasgart
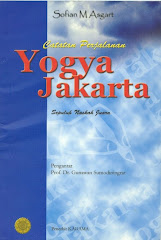



Tidak ada komentar:
Posting Komentar