| KOMPAS: Minggu, 5 Mei 2002 |
| |
| |
| |
| Media dan Budaya dalam Panggung Politik Orba Judul asli: Media, Culture, and Politics in Indonesia Versi Indonesia: Media, Budaya dan Politik di Indonesia Penulis: Krishna Sen & David T Hill Penyunting: Stanley, Penerjemah: Sirikat Syah Penerbit: Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Jakarta bekerja sama dengan PT Media Lintas Inti Nusantara, Cetakan pertama, Desember 2001 Tebal: (xv) 282 halaman STRUKTUR dominasi politik rezim Orde Baru (Orba) sangat tergantung pada dukungan sekaligus kepatuhan kelompok sub-ordinat yang menjadi objek dominasinya. Oleh karena itu Dedy N Hidayat mengantarkan buku ini dengan suatu ilustrasi bahwa betapapun kuatnya, rezim Orba senantiasa memerlukan mekanisme yang mampu secara terus menerus memproduksi legitimasi bagi hegemoninya. Proses untuk menyajikan rezim Orba sebagai realitas yang paling sah, secara implisit merupakan proses untuk membuat semua sosok tandingannya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, tidak konstitusional, tidak sesuai dengan 'kebudayaan nasional', ataupun tidak seharusnya ada. Media dan budaya memiliki peran strategis dalam proses reproduksi legitimasi tersebut. Pada tataran itu kesadaran individu mengenai Orba hampir sepenuhnya tergantung pada ekspresi media dan elemen industri budaya lainnya. Krishna Sen dan David T Hill, penulis buku ini, merujuk media dan elemen industri budaya itu pada tujuh pilar yang dianggapnya paling stategis. Ketujuh pilar itu adalah buku, pers, radio, televisi, sinema nasional, industri musik, dan internet. Dunia penerbitan buku dipandang sebagai salah satu locus yang signifikan dari globalisasi kehidupan kebudayaan Indonesia masa Orba. Oleh karena itu, tampak adanya upaya-upaya pemerintah Orba untuk menyusun etika, estetika, dan politik penerbitan di Tanah Air. Namun, dalam waktu yang bersamaan, tampak pula resistensi atasnya, terutama melalui karya sastra 'bawah tanah'. Dari perspektif ekonomi, sastra seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting dalam dunia penerbitan di Indonesia. Namun demikian, Krishna dan David melihat justru dari sinilah gugatan kebudayaan yang menentang parameter ekonomi dan politik yang diatur pemerintah Orba dimunculkan. Pramoedya Ananta Toer dan Wiji Thukul dalam pandangan Krishna dan David, merupakan dua sosok penting yang buku-buku karyanya menjadi tonggak perlawanan terhadap rezim Orba. Dalam skala global, bahkan, karya sastra sering menjadi titik awal masuk bagi pihak asing untuk melihat kebudayaan Indonesia. Krishna dan David tampak memilah pers (media cetak koran dan majalah) dari radio dan televisi. Ia melihat pers sebagai medium yang paling memusatkan perhatian pada perolehan dan penyebaran informasi dibanding media lainnya. Oleh karena itu, rezim Orba melakukan berbagai pengekangan yang sangat ketat lewat UU Pokok Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan peraturan lainnya. Pembreidelan majalah Tempo dan Editor merupakan contoh 'keberhasilan' Orba, namun sekaligus sebagai tonggak baru media perlawanan terhadap rezim Orba itu sendiri. Lahirnya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Tempo Interaktif, dan pers maya lainnya, telah menambah deretan perlawanan kelas menengah. Radio dan televisi tentu punya peran strategis pula dalam hal ini. Sejarah mencatat, radio menjadi pusat perebutan informasi. Letkol Untung memilih RRI sebagai gedung publik pertama yang dikuasainya sekaligus 'memproklamirkan' kemenangan Dewan Revolusi, dan kemudian Soeharto merebutnya kembali keesokan harinya seraya menyiarkan kepemimpinannya atas angkatan bersenjata. Meskipun secara akademis radio mendapat perhatian yang jauh lebih sedikit dibanding media lainnya, kenyataan menunjukkan radio merupakan media massa utama bagi banyak wilayah pedesaan Indonesia. Lebih daripada medium lainnya, radio muncul di era Orba dengan kerangka hukum dan ekonomi yang menolak kontrol monopolistis modal besar dan kontrol pusat dari Jakarta. Dengan demikian, radio menjadi signifikan dalam proses demokratisasi. PP No. 55/1970 memang secara tegas mengatur fungsi sosial radio 'sebagai alat pendidik, alat penerangan, hiburan dan tidak dpergunakan... untuk kegiatan politik'. Tapi pada kenyataannya, radio menjadi sumber opini publik yang beraneka ragam. Radio juga menjadi media strategis bagi para aktor politik untuk menjangkau publik penentu suara yang beraneka ragam, termasuk menyebarkan ide-ide reformasi ke pelosok-pelosok menjelang tumbangnya rezim Orba. Jika radio dipandang sebagai sektor informasi yang sangat tak terpusat (decentralized) maka televisi sebaliknya, ia merupakan media yang paling dikontrol ketat dari Jakarta. Sepanjang masa Orba, televisi terus dipacu untuk mempromosikan persatuan nasional, seperti tersirat dalam semboyan TVRI: "menjalin persatuan dan kesatuan". Demikian pula televisi swasta dikontrol secara ketat agar tidak menebar informasi yang mengandung benih-benih perlawanan, terutama 'muatan lokal' yang mengarah ke unsur-unsur disintegratif. Kekhawatiran pemerintah Orba yang berlebihan itu, lebih mentolerasi masuknya budaya-budaya luar lewat paket acara impor. Telenovela, film India, kartun Jepang, menyerbu pemirsa di samping film dan musik Amerika yang makin diakrabi pemirsa Indonesia. Ironisnya, lewat tayangan-tayangan asing itu justru tidak sedikit pemirsa Indonesia mendapat ide-ide perlawanan dan pemberontakan. MacGyver merupakan salah satu contohnya. Film seri TV AS yang ditayangkan RCTI ini banyak digemari pemirsa Indonesia karena dianggap selalu membela hak-hak azasi manusia. Di sisi lain, hadirnya televisi swasta di Indonesia telah melonggarkan sedikit cengkeraman negara atasnya. Lahir dalam atmosfir persaingan, program televisi swasta di asah ke tujuan yang agak berbeda. Salah satunya yang utama adalah mendapatkan pemirsa bagi para pengiklan. Ideologi ekonomi ini sangat menguntungkan ketika ketidaksetujuan terhadap kepemimpinan Soeharto telah mulai mewabah menjadi mode di antara kelas menengah. Dalam kondisi seperti itu, pemirsa tentu bisa melihat dan menyaksikan lebih banyak ragam tayangan dari sebelumnya. Sinema nasional yang sebelumnya sering tampil penuh 'pesan sponsor' memunculkan gairah baru, misalnya, dengan hadirnya Sineas Garin Nugroho yang sebelumnya dianggap 'terlalu berani' dan kontroversial. Di dunia musik, konser 'pesanan' pemerintah mulai mendapat perlawanan. Pertunjukan Iwan Fals yang diikuti grup musik lainnya, seperti Pas (Bandung), Boomerang (Surabaya), Slank seringkali memukau penonton dengan lagu-lagu protes penuh perlawanan. Internet mendapat perhatian tersendiri menyongsong runtuhnya rezim Orba. Krishna dan David menilai, bukan wacana politik di internet yang penting, namun adanya rasa bahwa apa pun dapat dikatakan dengan bebas. Dalam konteks ini internet berhasil memecahkan sensor dan pembatasan pada kebebasan berekspresi yang diterapkan pemerintah Orba. Namun, dalam konteks yang lain, Sentot E Baskoro (1988) melihat 'manfaat langsung' internet dalam perjuangan politik menjelang runtuhnya Orba. Internet saat itu dimanfaatkan secara ekstensif oleh kaum oposisi kelas menengah perkotaan, terutama mahasiswa. Mereka menggunakan internet untuk merencanakan gerakan dan mengukur dukungan internasional dalam membangun demonstrasi nasional yang besar, yang akhirnya menumbangkan rezim Soeharto. Pada hari-hari terakhir, beberapa mahasiswa yang menduduki gedung parlemen memakai komputer laptop untuk mengirimkan berita secara online, sementara tentara dengan ketat menjaga di sekeliling mereka. Di sini tampak bahwa sifat teknologi internet tak terantisipasi oleh mekanisme kontrol negara. *** BUKU ini setidaknya memiliki dua kekuatan. Pertama, asosiasi dan akomodasi persoalan. Krishna dan David memiliki kekayaan wawasan untuk membandingkan berbagai fenomena di Indonesia dengan dunia luar, terutama Amerika, Eropa, dan Australia. Koes Plus diasosiasikan dengan The Beatles. Dangdut Rhoma Irama digambarkan sebagai perpaduan antara Jimmy Hendrix dan Rick Wakeman dengan rebana Betawi. Buku Nyanyi Sunyi Seorang Bisu karya Pramoedya dibandindgkan dengan Gulag Archipelago karya Solzhenitsyn. Kedua, kedua penulis mampu memotret intrik keluarga dan kroni Cendana dalam dunia pertelevisian Indonesia, dan bisa mengapresiasi aktivitas sebuah stasiun radio kecil yang berada di daerah terpencil: Radio Terunajaya di Pameungpeuk, sebuah kecamatan di ujung selatan kota Garut, Jawa Barat. Bahkan, ia 'berhasil' menghitung jumlah warnet di Yogyakarta beserta harga sewa per jam dan per menitnya secara rinci dan teliti (halaman 231-233). Namun, kerincian yang berlebihan itu membuat mereka lengah data yang lebih primer. Ia menyebut empat koran daerah tertua dan terkuat pada halaman 79 baris 2-4 tanpa menunjuk secara jelas. Tentang siaran lagu-lagu berbahasa daerah (halaman 79) ia menulis tak ada bahasa daerah lain selain Jawa". Seingat saya, di tahun 1996/7, TVRI Bandung punya serial drama Bojongrangkong dan paket acara Wayang Golek garapan dalang Asep Sunarya dalam bahasa Sunda. Selain itu ada sejumlah kelemahan lain baik teks maupun foto. Meski demikian sebagai suatu kajian akademis buku ini sangat penting untuk disimak. Sofian Munawar Asgart Ketua Yayasan Cendekia, Jakarta. |
Minggu, 14 Juni 2009
resensi buku
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
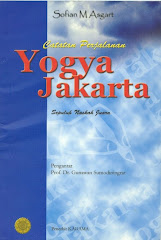



Tidak ada komentar:
Posting Komentar